
LIPUTAN KHUSUS:
FSC Harus Pastikan Kerusakan Wilayah Masyarakat Terpulihkan
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Kala Korporasi hadir merampas tanah mereka, nyaris tak ada yang tersisa selain lingkungan hidup dan kehidupan sosial yang rusak.
Hutan
Jumat, 21 Oktober 2022
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Konversi dan eksploitasi hutan alam oleh korporasi besar di Indonesia telah memberikan dampak besar bagi masyarakat. Kala Korporasi hadir merampas tanah mereka, nyaris tak ada yang tersisa selain lingkungan hidup dan kehidupan sosial yang rusak.
Petrus Kinggo, masyarakat adat asal Dusun Kambenap Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua mengaku merasakan langsung dampak buruk perusakan hutan, seperti sungai menjadi rusak, hutan tempat berburu hilang, dan bencana pun terus bermunculan.
“Kami, menyaksikan bagaimana aktivitas perusahaan sawit dan hutan tanaman industri telah menghancurkan sungai tempat kami mengambil air, hutan tempat kami memperoleh makanan dan rumah," ungkap Petrus, dalam pernyataan tertulis yang diterima Betahita.
"Masyarakat adat itu, hidupnya menyatu dengan tanah dan hutan, kalau hutannya hilang, kita hidup bagaimana,” lanjutnya.

Sebagai gambaran, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, menunjukkan, kurang lebih sekitar 11,2 juta hektare Kawasan Hutan di Indonesia telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Tanaman--sebelumnya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman--dan seluas 18,4 juta hektare lainnya dibebani PBPH Hutan Alam.
Penguasaan lahan skala besar oleh korporasi yang dinyatakan dalam angka hektare data KLHK itu tentu jadi peringatan bagi masyarakat manapun yang hidupnya menyatu dengan hutan, tentang kehancuran lingkungan dan ruang hidupnya. Seharusnya ada yang bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh masyarakat adat seperti Petrus Kinggo ini.
Hal itu pula yang kemudian memantik munculnya desakan kepada Forest Stewardship Council (FSC)--lembaga nirlaba yang secara luas diakui di antara organisasi masyarakat sipil, konsumen, dan bisnis sebagai sistem sertifikasi hutan paling ketat untuk mengatasi tantangan deforestasi, iklim, dan keanekaragaman hayati--agar memutuskan sesuatu yang akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat adat.
Salah satunya dengan penguatan kerangka kerja pemulihan lingkungan dan sosial (Mosi 45). Mewajibkan semua calon pemegang sertifikasi FSC untuk terlebih dahulu menyelesaikan hingga tuntas persoalan lingkungan dan sosialnya sebelum kembali berasosiasi dengan FSC.
Keputusan dan kebijakan FSC dianggap akan mempengaruhi pengelolaan hutan dunia, termasuk Indonesia. Apakah kondisi yang dihadapi masyarakat akan selesai, atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk.
Desakan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil kepada FSC ini punya alasan kuat. Salah satunya adalah disepakatinya perubahan batas waktu konversi hutan (deforestasi) dari 1994 menjadi 2020 yang akan diterakan FSC, hasil dari Rapat Umum Forest Stewardship Council (FSC- General Assembly) digelar di Nusa Dua, Bali, 9-14 Oktober 2022 kemarin.
Perubahan batas waktu konversi hutan alam ini telah membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan yang telah membuka lebih dari 2 juta hektare hutan alam Indonesia dan berkonflik dengan ratusan masyarakat adat maupun masyarakat tradisional, seperti, Asia Pulp and Paper (APP), APRIL, Djarum dan Korindo, untuk dapat kembali bergabung, dan mendapatkan keuntungan dari sertifikasi ini.
Kondisi ini menempatkan reputasi FSC dalam pertaruhan, jika peluang bergabungnya perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tidak dibarengi dengan implementasi secara utuh dan pemantauan yang ketat pelaksanaan kerangka pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial.
Sugiarto, masyarakat Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengharapkan penilai Independen harus dilibatkan sejak awal saat mengidentifikasi pemangku kepentingan atau pemegang hak yang terdampak dan area terdampak. Informasi harus disampaikan secara utuh dan dapat diakses publik. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya keberpihakan pihak ketiga, ketidak adilan dan mencegah persetujuan dengan paksaan.
Hal senada disampaikan Aidil Fitri dari Hutan Kita Institute (HaKI) yang hadir sebagai pembicara pada gelaran Rapat Umum FSC pekan lalu. Aidil mengatakan persoalan konversi dan pemulihan merupakan isu penting. Sebab persoalan hari ini adalah isu kepercayaan terhadap korporasi dan juga sertifikasi.
“Kami, menaruh harapan pada FSC, untuk menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat,” katanya.
Isu kinerja keberlanjutan serta penyelesaian persoalan sosial di tingkat tapak seharusnya menjadi acuan dalam segala pertimbangan FSC. Mulai dari penyusunan dan penetapan kerangka kerja pemulihan hingga pelaksanaannya.
Ke depan, implementasi atas kerangka pemulihan akan menjadi ukuran, apakah FSC dapat mengontrol pemegang logo-nya untuk melakukan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab atau tidak. Jika tidak, FSC akan kehilangan reputasinya sebagai skema pelindung hutan dan masyarakat adat dunia.
"Masyarakat adat adalah perawat hutan terbaik, yang mana mereka merawat, menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumber penghidupan mereka," kata Martha Dod, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, yang hadir di Nusa Dua, Bali, mendampingi masyarakat adat Long Isun yang terdampak dari perusahaan HPH milik Harita Group di Mahakam Hulu.
Sebelumnya, pada 9-14 Oktober 2022 kemarin, perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, hadir pada Rapat Umum FSC, di Nusa Dua, Bali. Perhelatan berkala yang menjadi momen penting bagi organisasi dengan keanggotaan dari berbagai latar belakang diantaranya non government organization, bisnis, akademisi, peneliti dan masyarakat adat, yang berasal dari lebih 40 negara, yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab.
Mereka hadir untuk menyampaikan kekhawatiran dan menceritakan dampak atas konversi dan eksploitasi hutan alam oleh korporasi besar di wilayah mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menguasai dan merusak wilayah adat yang sangat luas dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang besar. Masyarakat adat yang hadir tersebut berasal dari Sumatera, Kalimantan dan juga Papua.


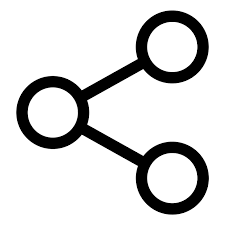 Share
Share

