
LIPUTAN KHUSUS:
Greenpeace: 600 Perusahaan Sawit Beroperasi dalam Kawasan Hutan
Penulis : Kennial Laia
Laporan terbaru Greenpeace Indonesia mengungkap, 600 perusahaan kelapa sawit beroperasi di dalam kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan kawasan konservasi.
Sawit
Jumat, 22 Oktober 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Greenpeace Indonesia menyatakan setidaknya terdapat 600 perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di dalam kawasan hutan. Selain itu, seluas 90.200 hektare area dalam hutan konservasi telah dikonversi menjadi tanaman monokultur tersebut.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan korporasi sawit beroperasi hampir di semua kategori kawasan hutan, termasuk taman nasional, suaka margasatwa, bahkan situs UNESCO, mulai dari Sumatra hingga Papua. Ini termasuk kasus penggundulan area hutan Gunung Melintang di Kalimantan Barat dan kasus Suaka Margasatwa Bakiriang, Sulawesi Tengah.
“Kebun-kebun perusahaan tersebut memiliki luas di atas 10 hektare di dalam kawasan hutan,” kata Arie dalam peluncuran laporan kepada media, Kamis, 21 Oktober 2021.
“Tanaman sawit juga ditemukan di dalam area hutan lindung dan kawasan konservasi. Padahal kedua jenis hutan ini memiliki fungsi perlindungan pada ekosistem sehingga penting untuk dilindungi,” tambahnya.

Laporan terbaru Greenpeace memetakan tutupan kelapa sawit nasional di angka 16,24 juta hektare, tak jauh berbeda dengan angka yang dikeluarkan pemerintah sebesar 16,38 juta hektare.
Dari luas tersebut, lembaga nonprofit tersebut menganalisis terdapat 3,12 juta hektare perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir 2019. Seluas 1,55 juta hektare dikembangkan perusahaan perkebunan. Sisanya, seluas 1,56 juta hektare, merupakan perkebunan swadaya mandiri.
Berdasarkan tipe kawasan hutan, perkebunan kelapa sawit di hutan konservasi seluas 90.200 hektare dan hutan lindung 146.871 hektare. Sementara itu, di hutan produksi terbatas terdapat 473.906 hektare kebun sawit.
Kebun sawit liar terbesar berada di hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan produksi. Masing-masing seluas 1.008.849 hektare dan 1.398.978 hektare.
Analisis Greenpeace juga mengindikasikan bahwa per 2019, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Indonesia mencakup 183.687 hektare yang sebelumnya terpetakan sebagai habitat orangutan, serta 148.839 hektare habitat harimau sumatra.
Menurut Arie, ekspansi sawit korporasi terhadap kawasan hutan terjadi pada 2001. Namun periode paling masif adalah 2003-2009. Perambahan terus terjadi hingga 2019, bahkan setelah implementasi moratorium sawit berlaku.
“Perusahaan-perusahaan yang merambah hutan pada periode tersebut terhubung pada setidaknya lima grup konglomerasi, termasuk termasuk Best Agro Plantation, Sinar Mas, Wilmar, Musim Mas, dan Citra Borneo Indah,” tutur Arie.
Riau dan Kalimantan menjadi contoh paling mengerikan terkait penanaman kelapa sawit secara ilegal di kawasan hutan. Dua provinsi tersebut belum menyesuaikan rencana tata ruang agar selaras dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).
Proses ini, dimulai pada 1980-an, merupakan payung kebijakan kehutanan pertama di Indonesia yang memetakan batas-batas definitif antara berabgai kategori lahan yang dikelola Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK).
Sumatra dan Kalimantan juga memiliki tutupan sawit dalam kawasan hutan paling banyak, masing-masing 61,5 persen dan 35,7 persen. Di Sumatra, ada Provinsi Riau yang memiliki 1.231.614 hektare sawit dalam kawasan hutan serta Kalimantan Tengah seluas 817.693 hektare.
Sawit dalam kawasan hutan di dua provinsi tersebut mencakup dua pertiga dari total nasional. Sumatra dan Kalimantan juga mengalami tingkat deforestasi yang tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir, masing-masing pulau kehilangan 4 juta hektare di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Sebelumnya kolaborasi riset dan peliputan media dan peneliti (Betahita, Tempo, Mongabay Indonesia, Auriga Nusantara, dan peneliti independen) mengungkap sawit dalam kawasan hutan menjadi salah satu sumber hilangnya penerimaan pajak sektor sawit, baik pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai, maupun pajak penghasilan (PPh) badan.
Potensi belasting yang hilang dari usaha perkebunan kelapa sawit selama ini diperkirakan mencapai Rp 22,8 triliun per tahun. Namun pada kenyataannya, negara hanya menerima sepertiga dari total tersebut. Angka potensi diperoleh dari selisih antara perhitungan potensi konservatif dan rata-rata realisasi 2016-2020.
“Masalah ini harus diselesaikan tapi malah jadi abu-abu sehingga ekspansi sawit di dua provinsi menjadi tinggi. Ini sering dimanfaatkan, melalui skema pemutihan atau ketelanjuran. Padahal dalam prosesnya penegakan hukum sangat lemah,” tandas Arie.
Membuka perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Aktivitas lain seperti memungut, menampung, dan mengolah TBS dari kebun di dalam kawasan hutan juga haram menurut beleid tersebut.
Namun, menurut Arie, beberapa regulasi justru mengizinkan kebun sawit dalam kawasan hutan milik korporasi dibiarkan atau tanpa mekanisme penyelesaian yang adil. Dia menyebut aturan seperti Peraturan Pemerintahn (PP) Nomor 60 Tahun 2012 sebagai bentuk ‘pemutihan’ pertama yang memaafkan pelanggaran perusahaan.
Aturan ini merupakan amendemen PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan ini memungkinkan perusahaan melepaskan lahannya dari kawasan hutan selama enambulan, atau melaksanakan tukar-menukar kawasan hutan.
Pada 2015, aturan ini kembali diamendemen. Perusahaan memperoleh waktu lebih panjang yakni satu tahun untuk mengajukan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan tukar-menukar lahan.
Kebun-kebun di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi juga dapat dilegalisasi melalui daur tanam yang dapat berlangsung selama puluhan tahun. Ketentuan ini batal pada 2019 setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat menantang peraturan ini di Mahkamah Agung.
Yang paling baru, kata Arie, adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law, yang mengubah ketentuan dari Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa tenggang hingga tiga tahun, dan mengganti sanksi pidana dengan sanksi administratif. Menurut Arie, ketentuan ini semakin membuka kesempatan bagi perusahaan menguasai kawasan hutan.
“Aturan ini memutihkan sawit-sawit dalam kawasan hutan di wilayah konservasi serta menghapus sanksi pidana dengan mengutamakan sanksi administratif, termasuk dalam aturan turunannya di KLHK,” pungkas Arie.


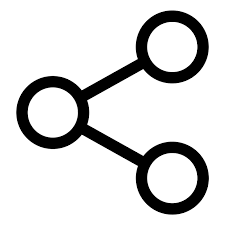 Share
Share

