
LIPUTAN KHUSUS:
Food Estate Bikin Ruang Hidup Orang Asli Papua Terampas
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Food estate di Bumi Cendrawasih ini dikhawatirkan akan mengakibatkan ruang hidup Orang Asli Papua menjadi terampas.
Agraria
Selasa, 29 Juni 2021
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Sejumlah wilayah jadi sasaran Program Lumbung Pangan atau Food Estate pemerintah, salah satunya Provinsi Papua. Suara kehawatiran pun muncul. Food estate di Bumi Cendrawasih ini dikhawatirkan akan mengakibatkan ruang hidup Orang Asli Papua menjadi terampas.
Kekhawatiran nasib masa depan ruang hidup Orang Asli Papua, dan deretan permasalahan baru yang muncul atas hadirnya Program Ketahanan Pangan di Papua ini terurai dalam Kertas Posisi yang diterbitkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berjudul Food Estate di Papua: Perampasan Ruang Berkedok Ketahanan Pangan?, pada Senin (28/6/2021) kemarin.
Dalam Kertas Posisi tersebut Walhi menilai pemerintah menganggap Papua yang kaya hanya sebagai objek pembangunan. Kapitalisme dengan beragam wajah hadir dan diproteksi melalui berbagai produk hukum dan kebijakan. Perjuangan panjang dan suara lantang Orang Asli Papua untuk merebut daulat atas tanah, air, udara dan hak dasar lainnya kembali menemui tantangan yang bernama kebijakan pembangunan food estate. Papua seolah tanah tak bertuan.
Masyarakat Adat, Orang Asli Papua hingga Pemerintah Otonomi Khusus sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan program food estate. Pemerintah merencanakan kembali program food estate di Papua. Luasnya sekitar 2.684.680,68 hektare. Lokasinya berada di Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi.

Dari luasan tersebut, 2.684.461,54 hektare di antaranya merupakan kawasan hutan, yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi. Sisanya Areal Penggunaan Lain (APL). Artinya, bila program ini benar-benar dijalankan, akan ada lebih dari 2 juta hektare kawasan hutan yang akan dikonversi dan dibabat.
Hal ini jelas akan memperpanjang daftar deforestasi di Tanah Papua. Pada 2019, Papua setidaknya telah kehilangan sekitar 22.700 hektare hutan primer. Ini sebanding dengan 14,8 juta ton emisi CO2.
Rerata luas deforestasi Indonesia antara 2001-2019 sekitar 500 ribu hektare. Pada 2019, tutupan hutan primer tersisa sekitar 86 juta hektare, atau berkurang sekitar 9,6 juta hektare sejak 2001.
Setidaknya sekitar 1,4 juta hektare hutan alam tersisa di lahan perkebunan sawit di Tanah Papua, dan semuanya menunggu untuk dikonversi jadi perkebunan sawit. Bila proyek ini tetap dijalankan, maka kurang lebih 1,4 juta hektare deforestasi akan terjadi tanah Papua. Bahkan, rencana food estate yang berada di lokasi dengan tingkat bahaya banjir tinggi seluas 596 ribu hektare.
Program food estate di Papua bukan suatu hal baru. Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program serupa telah coba dilaksanakan. Dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Bercermin dari MIFFE, program ini bukannya meraih sukses, malahan melahirkan banyak persoalan dibanding manfaat bagi Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua. Sagu sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Papua dikesampingkan. Pemerintah malah mengembangkan komoditi yang sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pada masyarakat Papua.
Hal ini kian diperparah, yang mana MIFFE malah meminggirkan kekhususan Papua, dimulai dari desain kebijakan yang sentralistik, hingga abai pada hak atas tanah dan sumber daya alam Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua. Program tersebut malah memberi akselerasi penguasaan ruang pada korporasi.
Paling tidak terdapat 36 perusahaan yang terlibat menggarap food estate dalam program MIFEE. Tujuh perusahaan diantaranya telah memulai kegiatan usaha pertanian skala luas, yakni Wilmar International, Medco Group, Rajawali Group, Murdaya Poo Group, PT. Bangun Tjipta Sarana, Sinar Mas Group dan Artha Graha Group.
Mengutip tulisan Goldstein, mengenai refleksi terhadap kebijakan food estate di Indonesia, proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah, yang merupakan Mega Rice Project sepanjang tahun 1995-1999, dianggap sebagai salah satu penyebab bencana lingkungan hidup terbesar dalam rekam jejak Indonesia. Karena selain mengakibatkan kebakaran lahan gambut skala besar, proyek tersebut bahkan tidak menghasilkan beras.
Pengembangan MIFEE juga tidak luput dari permasalahan. Obidzinski dkk. menguji klaim pemerintah yang menyatakan bahwa MIFEE akan memiliki dampak lingkungan yang terbatas. Kenyataannya sekitar 50 persen lahan pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan sekunder.
Berdasarkan alokasi lahan konsensi, proyeksi total emisi karbon yang terlepas diperkirakan mencapai 770 juta ton per tahun yang 70 persennya berasal dari konversi area hutan. Selain itu juga ditemui hilangnya keanekaragaman hayati.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup di Provinsi Papua, pasal 63 UU Otsus Papua menyebutkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d sampai g Perdasus Nomor 21 Tahun 2008, bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan, d. mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan; e. menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi; f. mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati; dan g. mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.
Sayangnya, kehadiran P.24 justru tidak sejalan dengan amanat pasal 63 UU Otsus Papua maupun Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 serta pengalaman berbagai proyek food estate di Indonesia.
Hal ini terlihat dari adanya istilah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Cepat yang dapat menggantikan posisi KLHS serta mereduksi esensi dari KLHS sebagai kajian sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Padahal sejatinya, KLHS difungsikan sebagai dasar pengkajian, pembentukan alternatif dan rekomendasi kebijakan tata ruang dan pembangunan untuk menjamin keberlanjutan sebagaimana amanat pasal 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Mengingat sifatnya yang memegang kualifikasi penting dan tinggi dalam pengambilan keputusan strategis, maka manakala KLHS menyatakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah terlampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Namun, faktanya, dalam proyek food estate, KLHS justru dilakukan setelah lokasinya ditentukan.
Aiesh Rumbekwan, Direktur Eksekutif WALHI Papua menyebut kegagalan proyek food estate pada rezim sebelumnya tidak membuat pemerintah jera mengulang kebijakan dan program serupa. Menurutnya, belajar dari pengalaman MIFFE, pembangunan food estate yang rakus lahan menjadi salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak dasar Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua. Mengulang program ini dengan kebijakan baru sama artinya, mendesain sebuah skema pelanggaran HAM baru terhadap Masyarakat Adat dan Orang Asli Papua.
"Program ini akan semakin menjauhkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas tanah dan hak untuk hidup. Bahkan potensi konversi dan deforestasi akan menjauhkan relasi sakral kami dengan alam. Bagi kami orang Papua, hutan seperti mama, ia menyediakan berbagai kecukupan, bahkan beragam ritual bergantung pada kelestarian alam," kata Aiesh.
Argumentasi pemerintah mendorong program food estate bersandar pada alasan ketahanan pangan, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat dan lingkungan hidup. Apalagi bertentangan dengan kekhususan Papua yang ditegaskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dan beragam Perdasus Papua.
"Berdasarkan kajian perundang-undangan kekhususan Papua dan perumusan kebijakan program food estate yang tidak partisipatif merupakan sebuah pelanggaran terhadap otonomi khusus di Papua. Pemerintahan Joko Widodo seolah memilih jatuh pada lubang yang sama. Jatuh pada kesalahan penghormatan otonomi khusus, jatuh pada kekeliruan yang terjadi periode food estate pada program MIFFE," ujar Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi Nasional.
Bagi Walhi Nasional maupun Walhi Papua, penolakan terhadap program food estate merupakan suatu konsekuensi logis. Terlebih hal tersebut bukan merupakan solusi untuk menjawab persoalan pokok yang dihadapi Papua.
Satu-satunya cara bagi Pemerintah untuk memperlihatkan keberpihakannya terhadap Papua adalah menaruh fokus pada pekerjaan pemenuhan daulat Orang Asli Papua atas tanah, hutan dan hak lainnya. Kebutuhan terhadap produk hukum yang menegaskan pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak-hak Orang Asli dan Masyarakat Adat Papua merupakan kebutuhan mendesak. Pemerintah bersama Pemerintah Otonomi Khusus harus segera merealisasikan kebutuhan tersebut.
Berdasarkan paparan di atas, Walhi menilai proyek food estate yang diwacanakan pemerintah harus ditolak. Alasan ini berangkat dari pengalaman masa lalu, dimana proyek serupa yang pernah dijalankan selalu menemui kegagalan dan mengakibat dampak negatif pada manusia dan lingkungan hidup.
Walhi juga berpendapat, Program Food estate ini bahkan dapat dikategorikan sebagai cermin semakin kokohnya kuasa kapitalisme di Tanah Papua. Orang Asli Papua tidak ditempatkan sebagai manusia sesungguhnya, Tanah Papua dan masyarakatnya hanya diposisikan sebagai objek pembangunan.
Walhi menilai food estate hanya akan semakin mempermudah perampasan hak Orang Asli Papua atas tanah dan alamnya. Lebih jauh, program ini akan semakin memarjinalisasi Orang Asli Papua, menjauhkan bahkan memisahkannya dari identitas aslinya.
Semangat otonomi khusus bagi Provinsi Papua guna menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua juga diabaikan. Pelaksanaan program ini di Papua hanya akan mempertegas kedok palsu otonomi khusus.
Bagi Masyarakat Adat Papua, hutan adalah mama yang memberi kehidupan. Mencukupi kebutuhan dan menyediakan segala yang diperlukan. Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2), 28I ayat (3) dan 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menentukan negara berkewajiban mengakui, menghormati, dan melindungi Masyarakat Adat beserta hak-hak yang menyertainya.
Selanjutnya, Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menentukan pembangunan tidak mengabaikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang dalam amarnya menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan hak (masyarakat hukum adat) dan tidak lagi berstatus hutan negara.
Jauh sebelum lahirnya Putusan MK 35/2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) telah mengakui keberadaan masyarakat adat Papua. Pasal 1 huruf r UU Otsus Papua mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
Sedangkan Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
Kehancuran hutan dan alam Papua merupakan konsekuensi buruk program food estate yang sama artinya memperlihatkan komitmen buruk mitigasi perubahan iklim Indonesia. Program ini akan menaruh manusia beserta entitas lainnya dalam ancaman bencana ekologis dan perubahan iklim.
Food estate hanya sebuah program yang menguntungkan dan melayani ambisi oligarki, menajamkan kuku kuasa kapitalisme. Bukan untuk kesejahteraan Papua dan masyarakatnya.


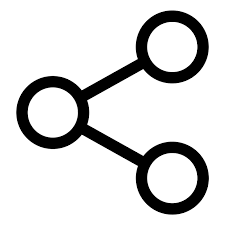 Share
Share

