
LIPUTAN KHUSUS:
Etika Sains dan Politik dalam Kebijakan Sumber Daya Alam
Penulis : Hariadi Kartodihardjo
Tujuan kebijakan yaitu menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat melalui proses berfungsinya tugas-tugas pemerintahan.
Kolom
Jumat, 12 Juni 2020
Editor :
BETAHITA.ID - Apa yang dapat dilihat atau dirasakan sehari-hari?
Tujuan kebijakan yaitu menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat melalui proses berfungsinya tugas-tugas pemerintahan yang secara hukum dan administrasi telah ditetapkan. Tetapi dalam praktiknya terdapat pilihan-pilihan karena ada perbedaan cara berpikir, kepentingan-kepentingan maupun bekerjanya jaringan yang dapat memperkuat atau bahkan memaksakan pilihan-pilihan itu melalui kekuasaan (Wolmer dkk 2006).
Dalam kondisi seperti itu, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan bisa terdapat bias birokrasi maupun terjadi titik buta (blind spot) (Bach dan Wegrich 2019). Birokrasi bekerja juga dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan, sehingga di dalam birokrasi dapat mempunyai tujuan sendiri dan tidak dapat bekerja secara sinergi dengan unit kerja atau lembaga negara lainnya. Namun, juga mungkin birokrasi tidak dapat melihat masalah-masalah yang dihadapi masyarakat akibat titik buta oleh padatnya tugas-tugas administrasi daripada berhubungan langsung dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.
Dengan begitu, peran regulasi atau undang-undang dan turunannya (rule in form)—yang seringkali lebih diandalkan untuk dapat memecahkan masalah—dapat kecil dapat besar, dan sisanya, yang menentukan implementasi regulasi tersebut (rule in use) diisi oleh faktor lain. Sebagaimana disebut Wolmer dkk (2006) sebelumnya, cara pikir (diskursus), kepentingan dan jaringan menentukan bagaimana kebijakan dibentuk dan dijalankan.

Dengan demikian, implementasi regulasi tersebut bersifat abstrak, selain penggeraknya tiga faktor yang disebut William Wolmer dkk itu, oleh Watts dan Peluso (2013) disebut karena sebagai peran “rezim kebenaran” yang biasanya mengejawantah ke dalam “rezim pengaturan”. Dalam hal ini perlu didalami kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kebijakan apa yang dibingkai dengan cara apa, serta mengatur perubahan apa dan ke arah mana; siapa yang sedang mengendalikan apa, melalui bentuk lembaga mana.
Dengan kata lain, pengetahuan (umum) dan ilmu pengetahuan serta kebijakan bukanlah semata-mata mewujudkan gagasan-gagasan mengenai masalah, solusi, mana yang benar atau mana yang salah, tetapi dapat menjadi atau digunakan sebagai sarana membangun suatu regim. Dalam kenyataannya rezim itu digunakan sebagai “alat pemaksa” yang cukup halus, karena daya paksanya sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat—berupa keyakinan-keyakinan, narasi kebijakan ataupun diskursus—melalui pengetahuan dan ilmu pengetahuan.
Pada titik ini, ilmu pengetahuan dapat tidak netral, karena ia disaring, dipilih dan ditetapkan hanya yang sesuai dengan tujuan suatu rezim atau kelompok tertentu. Dalam hal-hal tertentu bahkan terdapat “mesin kebohongan” (Block 2019) yang kini populer dengan istilah buzzer. Dalam buku “Post-Truth and Political Discourse” karya David Block itu, ia mensitir pendapat Proctor, sejarawan sains, yang menyebut beberapa jenis ketidaktahuan yang dapat dibedakan:
(a) ketidaktahuan sebagai “primitif” atau asli tidak tahu, (b). ketidaktahuan sebagai “kehilangan ranah” atau “pilihan selektif”, akibat kurangnya perhatian, tidak tersedianya informasi atau bahkan pilihan, (c) ketidaktahuan sebagai praktik strategis, akibat tindakan kerahasiaan atau sensor, dengan maksud menyembunyikan informasi; dan (d). ketidaktahuan sebagai “konstruksi aktif”, sebagai hasil dari upaya bersama dari sumber yang sah (misalnya dari ilmuwan, pakar) untuk menipu, dan untuk memproduksi dan memanipulasi pemahaman individu atau kolektif tentang hal-hal tertentu.
Tautan kebohongan pasti lebih kuat untuk dua jenis ketidaktahuan yang terakhir, sebagai “taktik strategis” dan “konstruksi aktif”. Kedua jenis ketidaktahuan inilah yang paling menarik perhatian, mengingat apa yang mungkin disebut gerakan backlash, atau bahkan gerakan kontra-intelijen, telah muncul ketika kepentingan ekonomi yang kuat telah menyadari adanya temuan ilmiah tertentu sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup jangka panjang mereka (Block 2019).
Pada titik itulah, isi kebijakan dan implementasi kebijakan dapat digunakan secara menyimpang, dalam arti tidak untuk memecahkan persoalan masyarakat luas, tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu, misalnya dalam hal memperoleh kekayaan dari sumberdaya alam. Dalam kondisi negara yang telah diisi oleh kepentingan-kepentingan kelompok yang sangat dominan, maka politik kebijakan sumberdaya alam dapat dipahami sebagai “rezim akumulasi”, dengan fokus pada pertanyaan siapa mendapat apa dan bagaimana distribusinya.
Dalam hal ini, dari evaluasi pelaksanaan gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam (GNP-SDA) yang dikoordinasikan oleh KPK misalnya, telah dibuktikan adanya hasil-hasil rezim akumulasi itu, baik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, perkebunan maupun pertambangan (KPK, 2018). Konseptualisasi kenyataan seperti itu misalnya dituangkan dalam buku “Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and Control”, karya Peter C. Kratcoski dan Maximilian Edelbacher (Editors; 2018), disebut bahwa agar dapat melibatkan diri dalam korupsi, seseorang harus memegang posisi kekuasaan yang dapat memberi orang kesempatan untuk menyalahgunakan posisinya atau gagal untuk mengambil tindakan pada hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab posisi tersebut. Penulis buku tersebut menggunakan “teori kenyamanan” yang dapat menjelaskan bagaimana korupsi dilakukan dan bagaimana hal itu tertanam dalam tradisi dan budaya birokrasi.
Untuk itu, corak kepentingan politik yang mempertahankan status quo akan selalu mendapat dukungan dari politik akumulasi laba, baik oleh perusahaan swasta, negara, ataupun elit individu. Ian Scoones (2016) mensitir David Harvey (2005) yang menyebut hal demikian itu sebagai “akumulasi dengan perampasan” atau penguasaan aset publik oleh pribadi-pribadi untuk mendapatkan keuntungan, yang pada gilirannya mendorong akumulasi dan meningkatkan ketidak-setaraan sosial termasuk ketidak-setaraan di hadapan hukum.
Pada bagian ini dapat dibuat pertanyaan konsepual: Apabila di dalam demokrasi terdapat proses politik yang menentukan ketiga rezim tersebut, apakah masalahnya dapat diselesaikan melalui proses politik yang sama?
Rasionalitas, Etika, Sains dan Narasi Kebijakan
Untuk hal-hal sederhana, pilihan rasionalitas sebagai dasar pemahaman terhadap fakta yang dipergunakan dalam penetapan kebijakan dan masalah yang akan diselesaikan dapat dengan mudah ditetapkan. Namun, situasi yang kompleks sering kali tidak mudah untuk menentukan pilihan itu, karena meskipun pihak tertentu setuju namun pihak lain dapat menolaknya.
Apabila rasionalitas diartikan sebagai proses yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan argumen-argumen yang bernalar dalam membuat dan mempertahankan pernyataan-pernyataan dalam suatu rancangan kebijakan, tidak hanya ditemukan bahwa banyak pilihan adalah rasional, tetapi juga dapat dilihat bahwa sebagian besar adalah bersifat multi-rasional. Itu berarti bahwa terdapat dasar-dasar rasionalitas ganda yang mendasari sebagian besar pilihan-pilihan kebijakan (Diesing dalam Dunn 2003).
Multi-rasional itu mencakup rasionalitas teknis, resionalitas ekonomis, rasionalitas legal, rasionalitas sosial, maupun rasionalitas substantif. Dalam prakteknya, pengambil keputusan cenderung tidak mempertimbangkan keseluruhannya, melainkan hanya memperhatikan alternatif-alternatif tertentu yang diperkirakan paling signifikan. Adanya alternatif itu bukan hanya berasal dari subyektifitas manusia, tetapi sumber kebenaran itu sendiri memang berbeda-beda. Perbedaan sumber kebenaran itu didasarkan antara lain oleh teori etika (Agoes dan Ardana 2009), misalnya terkait dengan pengertian-pengertian egoisme, utilitarianisme, deontologi dan teori hak, teori keutamaan dan etika teonom, yang dapat menjadi pilihan-pilihan sesuai dengan konteksnya ataupun kepentingannya.
Etika itulah yang semestinya digunakan untuk menyeleksi sains atau ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kebijakan dan masalah masyarakat yang akan dipecahkan. Karena senantiasa terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat dan lingkungannya sebagai bentuk perubahan sosio-ekologis, maka sains senantiasa diuji dari waktu ke waktu melalui verifikasi atas konsep-konsep yang digunakan (deduksi) terhadap kondisi nyata di lapangan (induksi), sehingga kebenaran sains itu sendiri selalu bersifat sementara dan selalu dapat diuji dan bukan atas dasar kepentingan.
Proses seperti itu, terutama yang terkait dengan sains yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dalam arti luas, menjadi tidak bebas nilai, karena fakta yang ditelaah bukan hanya fakta sebagai fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, tetapi juga fakta mengenai nilai-nilai atau baik-buruk, wajar-tidak wajar yang dirasakan masyarakat (Johnson 1986).
Dengan demikian mempelajari sains bukan hanya mengasah logika rasionalitas belaka, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kepekaan sosial, empati, dukungan, kepedulian, pembelaan, yang mungkin tidak pernah dapat digantikan oleh mesin.
Dalam kebijakan publik, antara rasionalitas, etika dan sains berkelindan membentuk apa yang biasa disebut sebagai narasi kebijakan (Jones dan McBeth 2010). Nasari itu menempati posisi epistemologi—asal, sifat dan jenis pengetahuan—yang menentukan benar-salah terhadap fenomena sosial yang dihadapi. Lebih jauh, narasi digunakan untuk mempengaruhi, memanipulasi dan memproduksi makna dalam kerangka pemikiran. Mencari narasi yang mendasari pemikiran atas adanya suatu kebijakan menjadi sangat penting, termasuk bagaimana agenda dibuat dan masalah ditetapkan dalam kebijakan itu, dan itu juga dapat diketahui bagaimana para pembuat dan pelaku kebijakan menyatakannya kepada publik melalui bahasa-bahasa yang digunakannya.
Kompleksitas persoalan dalam masyarakat serta adanya kepentingan-kepentingan dalam memperebutkan barang publik (fungsi hutan, air bersih dan lain-lain) dapat diketahui bagaimana pembuat kebijakan merespon hal itu melalui penetapan masalah berdasarkan narasi yang digunakannya. Penetapan masalah kebijakan biasanya didasarkan pada narasi berdasarkan suatu pandangan terhadap sesuatu yang telah berjalan dan diyakini kebenarannya. Di dalamnya juga berisi kepahlawanan, kejahatan dan korban serta perlawanan dengan kekuasaan antara yang buruk dan yang baik (Jones dan McBeth 2010).
Kekuatan kelompok penganut narasi tertentu dapat disebabkan oleh kesamaan ideologi, tingkat interaksi antar orang di dalam kelompok, maupun kemampuan kelompok itu untuk mengendalikan anggota-anggotanya agar tetap memahami dan mendukung narasi yang dianutnya. Kontestasi narasi juga pernah terjadi dalam pengelolaan gambut di Indonesia, dengan pertanyaan apakah lahan gambut dimanfaatkan atau dikonservasi. Terhadap pertanyaan itu apa yang dilihat oleh para ahli tanah/hidrologi, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli politik dapat berbeda-beda.
Karakteristik SDA, Karakteristik Sosial
Karakteristik adalah suatu keadaan yang sering kali tidak dapat diubah dalam jangka pendek, atau sepanjang suatu analisis kebijakan dibuat. Karakteristik sumber daya alam menentukan relasi antar manusia, misalnya sifat inkompatibel sumber daya alam, apabila dimanfaatkan oleh si A, maka si B tidak dapat memanfaatkannya. Tetapi karakteristik sumber daya alam juga dapat berupa “barang berdampak bersama” (join impact goods) misalnya pemandangan, yang dapat dinikmati seseorang tanpa mengurangi manfaat keindangan pemandangan itu bagi orang lain. Karakteristik seperti udara bersih, sungai bersih, bencana alam, juga mempuyai sumber interdependensi antar manusia dengan cara yang berbeda-beda (Schmid 1986).
Itu artinya, sifat-sifat sumber daya alam juga mengandung sifat-sifat barang publik yang menjadi kepentingan umum atau bersifat sosial. Karakteristik sosial yang biasa dipelajari yaitu mengenai sifat-sifat individualitas dan keragamannya, sifat komunitas yang terorganisir ataupun mudah-tidaknya melakukan “aksi bersama” yang dalamnya terdapat unsur-unsur trust, reputasi, akuntabilitas. Hal tersebut sangat penting diketahui untuk memastikan apakah kebijakan dapat berjalan atau tidak di dalam suatu kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini, tidak seperti dalam pendekatan hukum yang mana diasumsikan bahwa masyarakat sadar hukum dan harus mematuhinya, untuk pendekatan ini, di dalam masyarakat apa-apa yang hadir “dari luar”—termasuk regulasi— akan direspon sesuai dengan karakteristiknya (Shore dan Wright 1997). Seperti disebutkan sebelumnya, kedua faktor karakteristik sumberdaya alam dan sosialnya itu menjadi penentu berjalannya regulasi, melalui arena aksi oleh aktor-aktor yang terlibat Ostrom (1990, 2005).
Oleh karena itu, memahami kedua karakteristik tadi dalam proses penetapan masalah dan solusi kebijakannya menjadi sangat penting, agar prinsip kehati-hatian (precusionary principles) dapat diwujudkan, termasuk penerapan sifat-sifat sumber daya alam sebagai suatu sistem, sifat sebagai siklus makhluk hidup, maupun serta sifat keberadaan (existance value) yang dapat memberi jasa lingkungan secara cuma-cuma. Kelemahan yang ditemui saat ini yaitu bahwa sains lebih dikenali secara parsial, sehingga sumber daya alam direduksi menjadi komoditi yang bersifat inkompatibel.
Dengan kata lain, pasar lebih digunakan sebagai dasar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya alam yang mana pasar itu bekerja atas dasar besarnya modal, sehingga secara politik masyarakat lokal dan adat tidak mempunyai daya untuk masuk ke dalam pengambilan keputusan.
Kondisi di Indonesia: Kegagalan Institusional
Hal-hal yang diuraikan di atas bukan hanya didasarkan pada pendekatan konseptual, tetapi juga didasarkan pada bukti-bukti empiris dalam pembuatan dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (Kartodihardjo 2016). Hal lain yang belum disebutkan dalam 5 uraian mengenai etika, sains dan politik kebijakan ini, yaitu adanya persoalan kelembagaan/institusional yang cukup kronis.
Terkait dengan rule in use tersebut di atas, sering kali segala sesuatu telah diatur secara lengkap, bahkan kelengkapan institusional juga tersedia, namun berbagai bentuk program dan kegiatan ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Salah satu penjelasan yang mungkin terhadap kondisi demikian itu yaitu terjadinya kegagalan institusional (institutional failures; Steinberg, 2015).
Dalam hal ini, institusi melihat peraturan-perundangan dari isi pengaturannya sebagai cara sah untuk mencapai tujuan, yaitu kemampuan mengatur untuk dapat menyelaraskan perilaku masyarakat ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan mengatur itu sendiri sangat tergantung efektivitas proses interaksi sosial (Steinberg, 2015). Proses itu mencakup partisipasi dalam pembuatan peraturan yang menentukan rasa memiliki peraturan tersebut serta komunikasi, informasi, interpretasi dan pemaknaan isi peraturan berlangsung dan melibatkan pengetahuan dan pengalaman maupun jaringan kekuasaan (web of power) yang telah ada di masyarakat (Wolmer dkk 2006).
Apabila tidak terjadi interaksi sosial secara efektif dan ada kepentingan-kepentingan yang cenderung menolak peraturan itu, maka peraturan itu dapat kehilangan legitimasi, sehingga cenderung tidak dapat berjalan. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa baik-buruknya peraturan atau efektif-tidaknya peraturan mampu mengarahkan perilaku masyarakat, bukan hanya tergantung pada “kualitas” isi atau teksnya, melainkan tergantung pada efektivitas interaksi sosialnya.
Terjadinya kegagalan institusional sebagai penyebab terjadinya kerusakan dan ketidakadilan pemanfaatan sumber daya alam ada empat kemungkinan (lihat tabel berikut):
Anatomi Kegagalan Institusional dan Kategori Penyebab Deforestasi
| Kemauan Mewujudkan Kelestarian (sustainability will) oleh masyarakat (termasuk pengusaha) | Kemauan Mewujudkan Kelestarian (sustainability will) oleh Publik (Kebijakan Pemerintah) |
|
| Tinggi | Rendah | |
| Tinggi | I. TIDAK EFISIEN Korupsi, kekakuan birokrasi, kelemahan desain program | II. LEMAH Klientilisme, interprenership |
| Temuan KPK (2018) terdapat faktor penetapan key performance indicator, tidak berjalannya single salary system, serta tidak dijalankannya multi-year budget yang memungkinkan fleksibilitas inovasi progam sesuai kenyataan di lapangan. Dalam hal ini deforestasi secara de yure tidak menjadi disinsentif bagi lembaga-lembaga negara. | Di dalam lembaga-lembaga negara diisi oleh midle men atau eminant persons yang ikut mengatur perizinan dan pengambilan keputusan. Lembaga pseudo-legal ini masih banyak terdapat di daerah. Kondisi infrastruktur, informasi, maupun jaringan di lapangan dikuasasi oleh kelompok pengusaha besar atau kelompok ekstra-legal yang tidak mudah diketahui. | |
| Rendah | III. DILANDA KONFLIK Out of date, stigma, diabaikan | IV. TIDAK BERSEDIA Menghindari tujuan pengelolaan lingkungan |
| Masyarakat seringkali mempunyai stigma akibat hubungan mereka dengan unsur-unsur pemerintahan yang kemudian terjadi miskomunikasi atau adanya janji-janji yang tidak ditepati. Maka, apabila tidak terdapat mediator yang dapat mereka percaya, berbagai bentuk program pemerintah maupun non pemerintah akan diabaikan. Dalam situasi seperti ini, jika mereka terlibat deforestasi, seperti orang yang sudah kehilangan harapan terhadap peran positif pemerintah. | Deforestasi pada hutan-hutan di P jawa yang dikelola oleh Perhutani, mungkin dapat dikategorikan pada Kuadran IV ini. Hal itu disebabkan baik masyarakat maupun Perhutani tidak punya “kepentingan” untuk mempertahankan hutan. Hutan bagi BUMN itu tidak dianggap sebagai asset, sehingga apabila hilang tidak menyebabkan kerugian secara finansial. Sedangkan masyarakat membutuhkan ruang untuk menanam tanaman pertanian yang dapat dilakukan dengan menebang hutan. | |
Kuadran I : Faktor internal birokrasi pemerintahan. Ini memerlukan kajian, penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan rencana aksi mengenai: key performance indicator, tidak berjalannya single salary system, serta tidak dijalankannya multi-year budget yang memungkinkan fleksibilitas inovasi progam sesuai kenyataan di lapangan.
Kuadran II : Faktor sosial-ekonomi-politik perusahaan besar. Ini memerlukan tinjauan sumber-sumber investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang ada, relasi diantara perusahaan yang membentuk holding company, serta tinjauan beneficiary owner (BO) sesuai dengan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018.
Kuadran III : Faktor sosial-ekonomi-politik masyarakat. Ini memerlukan pemetaan sosial untuk mengetahui masyarakat yang pro dan kontra terhadap program pemerintah atau non pemerintah, serta jaringan yang bekerja di dalamnya.
Kuadran IV : Meletakkan nilai-nilai baru dalam pengelolaan sumberdaya. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan yang kadang-kadang memerlukan paksaan misalnya melalui penegakkan hukum atas tokoh-tokoh tertentu yang berpengaruh. Contoh perbaikan kelembagaan perusahaan Kereta Api Indonesia (KAI) dapat digunakan.
Institusi “tidak efisien" pada Kuadran I menunjukkan walaupun institusi negara dengan preferensi masyarakatnya menekankan perwujudan keseimbangan atau kelestarian, namun faktanya tidak dapat mencapainya. Dalam hal ini, Masyarakat menderita karena korupsi, masalah hubungan principal-agent, lingkungan peraturan yang “melarang” birokrasi berbuat inovasi atau program yang dirancang dengan buruk.
Pada Kuadran II yaitu institusi “lemah”, walaupun misi masyarakat termasuk pengusaha menekankan tujuan kelestarian, tetapi tidak menikmati dukungan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin akan berwirausaha membuktikan bahwa kelestarian dapat diwujudkan yang kemudian diterima oleh masyarakat. Dalam kasus lain, di mana perusahaan-perusahaan yang ditopang oleh negara—sebagai bentuk klientilisme—bahkan mengejar agenda yang bertentangan dengan kehendak publik dan berakibat tidak mampu memberi pelayanan seperti yang seharusnya.
Kegagalan institusional pada Kuadran III “dilanda konflik” menunjukkan ketidakcocokan antara kehendak masyarakat dengan arah kebijakan publik. Dalam hal ini, kita tidak harus hanya bertanya apakah berbagai lembaga memiliki tujuan yang sama, tetapi yang dipersoalkan yaitu perbedaan prioritas antar lembaga itu. Dalam kasus-kasus seperti itu, banyak lembaga hanya mempunyai visi misi kelestarian termasuk membuat berbagai kaukus lingkungan, merevisi peraturan-perundangan, sementara dalam praktiknya tidak mengarah pada visi misinya itu. Kegagalan institusional pada Kuadran IV “tidak bersedia” yaitu apabila kebijakan publik dan masyarakat memang sepakat bahwa mereka tidak akan mengejar kelestarian sumberdaya alam. Dalam hal ini, kegagalan hanya dari perspektif pengamat luar yang kepentingannya memang berbeda dari kepentingan pemerintahan dan masyarakat yang bersangkutan. Pengamat seperti itu mungkin ingin terlibat dalam peningkatan kesadaran atau menumbuhkan nilai-nilai baru, agar kelestarian menjadi tujuan.
Adanya persoalan penggunaan etika, sains, dan politik saat ini, tampak tidak segera dapat diatasi, yang disebut dalam literatur sebagai “dialogues of the deaf (dialog para tunarungu)” (M. J. van Eeten 1999). Dalam situasi seperti itu, adanya ide-ide baru maupun buku-buku inovasi pemerintahan kurang dapat membantu menyelesaikan masalah, akibat adanya tujuan dan mindset berbeda. Artinya, urusan persoalan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam bukan hanya peningkatan kecakapan/pendidikan SDM, tetapi juga soal penggunaan etika, sains, dan politik yang akut, yang harus diselesaikan.
Apabila di lihat kondisi Indonesia secara umum, nampak bahwa proses pembelajaran pelaksanaan etika, sains dan politik dalam pembuatan kebijakan sumberdaya alam masih mempunyai learning curve datar, bahkan cenderung menurun, yang disangga hanya oleh kasus-kasus leadership tertentu yang dapat diandalkan, tetapi bukan baiknya kondisi sistem sosial-politik dan demokrasinya. Indikasi itu dapat ditunjukkan apabila setiap orang di suatu lembaga negara bekerja sesuai dengan prosedur dan azas legalitas, tetapi lembaga itu belum dapat memenuhi tujuan-tujuan publik yang diembannya.
Masalah kegagalan institusional itu, sejauh ini, nampak belum berhasil dibenahi. Untuk itu, secara teknis pemecahannya dapat mengikuti empat kuadran Steinberg itu. Namun, apabila mengikuti tiga faktor penentu perbaikan kebijakan oleh Wolmer dkk (2006), fokus perhatian yaitu ke arah perbaikan cara berfikir sampai dapat membentuk perbaikan narasi kebijakan. Pada titik ini, kita mempunyai pertanyaan: Apakah berilmu dan beragama itu sarana untuk menjalankan perintah, atau sarana untuk merawat etika dan cara berpikir?

Dalam novel “Anna Karenina” karya Leo Tolstoy, penulis Rusia, yang diterbitkan secara berseri pada 1873-1877 di majalah The Russian Messenger, terdapat kata-kata “all happy families resemble each other, but every unhappy family is unhappy in its own way”. Untuk persoalan kebijakan ini mungkin dapat dikatakan sebaliknya, bahwa “...Program dan kegiatan yang gagal, gagal dengan cara yang sama. Karena tidak dapat menjalankan hal yang sesuai dengan kenyataan, akibat diikat oleh peraturan, kelembagaan dan iklim kerja dengan cara pikir yang sama. Namun, bagi yang dapat menghindari kegagalan, dalam arti masyarakat sasaran benar-benar merasakan hasilnya, dan bukan hanya keberhasilan administrasi, 8 keberhasilan itu akibat dilakukan dengan caranya sendiri-sendiri...” Itu berarti, pelaksanaan program dan kegiatan ditengah-tengah situasi saat ini, perlu diatasi dengan inovasi dan membentuk jaringan yang luas untuk menggeser cara pikir yang telah melembaga puluhan tahun itu.
Hariadi Kartodihardjo
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, IPB University.
Materi untuk Kuliah Umum Online oleh Badan Restorasi Gambut (BRG-RI), 11 Juni 2020.


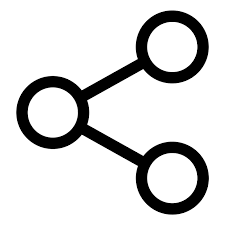 Share
Share
