
LIPUTAN KHUSUS:
Klaim Indonesiasentris Jokowi di Sidang MPR, Walhi: Kewalik
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Walhi menilai klaim keberhasilan pembangunan di era Jokowi kontradiktif dengan kondisi faktual.
Ekologi
Kamis, 22 Agustus 2024
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim berbagai pencapaian keberhasilan selama 10 tahun pemerintahannya. Namun, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) klaim keberhasilan tersebut kontradiktif dengan kondisi faktual yang menunjukkan pembangunan era Jokowi adalah pembangunan berwatak kolonial.
Walhi menyebut klaim keberhasilan, seperti pembangunan adil, merata, dan indonesiasentris, justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya melalui proyek strategis nasional (PSN).
Kebijakan strategis yang disebut sebagai modal transisi pemerintahan seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU IKN, justru menyebabkan perampasan ruang dan membebani APBN. Sementara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) malah menjadi alat pembungkaman dan pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat.
"Walhi memberikan beberapa catatan kritis pada beberapa bagian kunci pidato kenegaraan Presiden Jokowi," kata Fanny Tri Jambore, Kepala Divisi Kampanye Walhi, Jumat pekan lalu.

Pertama, kata Rere--sapaan akrab Fanny Tri Jambore, pembangunan adil, merata dan indonesiasentris tidak benar-benar terjadi. Pembangunan nasional di era Jokowi adalah pembangunan yang terpusat (Jakartasentris) dalam proses pengambilan keputusan (top-down approach).
Melalui ratusan PSN, pemerintah mendorong kerusakan lingkungan-memicu letupan konflik agraria yang merata ke berbagai wilayah lain mulai dari proyek Rempang Eco-City di Kepulauan Riau, Pertambangan dan kawasan industri nikel di Pulau Halmahera, Maluku Utara, Food Estate di Kalimantan Tengah, hingga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Pembangunan dari desa, pinggiran, dan terluar dalam praktiknya adalah perampasan tanah untuk PSN dan Bank Tanah, perluasan industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan dari Sumatera sampai Tanah Papua. Pembangunan dengan dalih pemerataan infrastruktur ini juga dinikmati oleh segelintir elit dan korporasi-korporasi besar, bukan oleh rakyat biaya.
"Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat selama 2020-2023 terdapat 115 konflik agraria yang disebabkan oleh PSN. Beberapa PSN seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan IKN justru menambah utang dan menguras APBN," kata Rere.
Kedua, pertumbuhan ekonomi nasional rerata sebesar 5 persen, Papua dan Maluku sebesar 6 persen dan Maluku Utara sebesar 20 persen. Pertumbuhan ekonomi ini tidak dinikmati oleh rakyat biasa dan ditebus dengan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang sama masif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir, lanjut Rere, belum mampu mengatasi angka ketimpangan ekonomi antara 1 persen penduduk terkaya dan 99 persen penduduk lainnya. World Inequality Database menyebut kelompok penduduk terkaya mengalami peningkatan kekayaan berlipat, sementara kelompok penduduk lainnya stagnan.
Beberapa tahun terakhir, masyarakat kelas menengah-bawah makin rentan menjadi miskin karena peningkatan harga kebutuhan pokok yang menyebabkan penurunan daya beli. Sementara pemerintah justru mendorong peningkatan pendapatan negara melalui kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Situasi ekonomi Indonesia juga dibayangi dengan peningkatan jumlah utang yang per April 2024 mencapai Rp8.338 triliun dengan Rp800 triliun di antaranya akan jatuh tempo pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Papua, Maluku, dan Maluku Utara yang ‘meroket’ dibayar dengan eksploitasi sumber daya alam dan mengorbankan keselamatan rakyat.
Secara khusus di Maluku Utara misalnya, Walhi Maluku Utara mencatat dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi seluas 26.100 hektare akibat pertambangan. Pencemaran lingkungan, kerusakan sumber penghidupan rakyat dan bencana ekologis dengan kerugian sangat besar harus ditanggung oleh warga.
"Keuntungan ekonomi dari industri-industri ekstraktif ini juga dinikmati segelintir orang, sementara kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan ditanggung oleh rakyat," ujar Rere.
Ketiga, daya tahan menghadapi pandemi covid dan perubahan iklim. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi covid justru mendapat kritik dari masyarakat dan pakar kesehatan. Kritik tersebut, sambung Rere, di antaranya, keterlambatan respon awal, respon pandemi tidak bersumber pada sains, pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran, korupsi bantuan sosial, prioritas ekonomi di atas kesehatan, dan pembatasan sosial longgar dan tidak merata.
Sementara terkait daya tahan pada perubahan iklim, tren bencana iklim selama satu dekade terakhir justru terus mengalami peningkatan. Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan produksi pangan dan harga bahan pangan akibat perubahan iklim adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Sedangkan pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi iklim masih sangat kecil.
"Pada sisi yang lain, perubahan iklim masih direspon dengan berbagai solusi palsu yang memperparah krisis melalui proyek seperti gasifikasi batu bara, CCUS (carbon capture utilization storage), biomassa dan lainnya," ujar Rere.
Kemudian keempat, Rere melanjutkan, terkait dengan hilirisasi, pengembangan industri-industri berbasis mineral kritis dan lapangan pekerjaan, yang harus diingat adalah bahwa jutaan hektare kawasan ekosistem penting telah dan akan mengalami kehancuran akibat pertambangan mineral kritis di Indonesia. Kementerian ESDM telah menetapkan sejumlah 47 jenis komoditas yang masuk sebagai mineral kritis di Indonesia.
Saat ini diperkirakan 3.641.119 hektare lahan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mineral kritis, dan sebagian besarnya berada pada wilayah yang penting secara ekologis. Diperkirakan 900.000 hektare lahan di Indonesia telah diberikan untuk izin pertambangan nikel. Lebih dari 600.000 hektare di antaranya berada dalam kawasan hutan.
"Pada 2021 saja, diperkirakan angka deforestasi akibat pertambangan nikel sudah melampaui 40.000 hektare. Jika keseluruhan kawasan yang diberikan izin pertambangan nikel dilakukan perubahan fungsi lahan, diperkirakan ada pelepasan emisi sebesar 83 juta ton CO2e," kata Rere.
Rere melanjutkan, klaim penambahan lapangan pekerjaan dari industri berbasis mineral kritis juga mesti diperiksa kembali. Karena dalam beberapa kasus, yang terjadi justru hilangnya pekerjaan dan sumber-sumber pendapatan masyarakat akibat operasi pertambangan untuk mineral kritis.
Dalam contoh konflik yang melibatkan PT Vale di Luwu Timur, imbuh Rere, terdapat 4.239 hektare kebun merica yang terancam digusur untuk kebutuhan ekspansi tambang nikel, padahal kebun merica tersebut menjadi sumber kehidupan utama hidup mereka, dan bahkan bisa memperkerjakan hingga 35.000 sampai 40.000 tenaga kerja setiap tahunnya.
"Hilangnya kawasan perkebunan ini tentu akan menghilangkan penghidupan warga dan para pekerja yang menggantungkan hidupnya di sana," ujar Rere.
Selanjutnya yang kelima, energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan. Rere menjelaskan, potensi energi terbarukan sebesar 3.600 GW belum dimanfaatkan secara serius oleh pemerintah. Pemerintah bahkan merevisi target bauran energi baru terbarukan dari 23 persen menjadi 17 persen pada 2025.
Implementasi energi terbarukan juga menghadapi tantangan dominasi energi fosil yang tinggi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara Indonesia justru terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2023, produksi batu bara mencapai 625 juta ton dan produksi batu bara 2024 diprediksi mencapai 628 juta ton. Transisi energi yang didorong oleh pemerintah juga masih dibayangi dengan berbagai proyek yang masih mendorong ekstraktivisme seperti gas, gasifikasi batu bara, biomassa dan lainnya.
Yang keenam, keberhasilan merumuskan dan merevisi UU strategis seperti UU Cipta Kerja, UU IKN, UU ITE, UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan lainnya. Rere menerangkan, kebijakan-kebijakan yang disebut dalam pidato Jokowi tersebut justru menjadi sumber masalah lingkungan dan pelanggaran HAM di Indonesia.
UU Cipta Kerja secara prosedural disusun dengan proses minim transparansi dan tanpa partisipasi bermakna. Sementara secara substansial, UU Cipta Kerja justru melemahkan perlindungan lingkungan, mengabaikan hak pekerja, dan memicu konflik agraria.
"UU Cipta Kerja mendapat penolakan keras dari publik dan diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Sayangnya pemerintahan Jokowi memaksakan implementasi UU Cipta Kerja melalui Perppu," ucap Rere.
Lebih lanjut Rere menerangkan, UU ITE yang lahir pada 2008 dan kemudian direvisi pada 2024 masih memuat pasal-pasal karet multi-tafsir yang berpotensi dipergunakan sebagai instrumen kriminalisasi. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) mencatat pada periode 2008-2022 terdapat 300 kasus kriminalisasi menggunakan UU ITE.
"Sementara UU IKN disahkan dengan proses supercepat tanpa ada partisipasi publik. Revisi UU IKN yang baru diundangkan satu tahun pada 2023 memiliki sejumlah catatan kritis seperti pembiayaan IKN yang bersumber dari APBN," kata Rere.


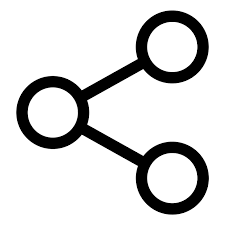 Share
Share

