Walhi: Perdagangan Karbon Berdampak Penggusuran Masyarakat
Penulis : Kennial Laia
Hutan
Jumat, 11 Agustus 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Perdagangan karbon yang digadang pemerintah sebagai salah satu solusi krisis iklim dinilai tidak tepat. Sebaliknya, mekanisme ini berpotensi menggusur dan merampas tanah dan hutan yang dikelola masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dalam kertas posisi terbarunya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama sejumlah organisasi nonprofit lainnya mengungkapkan penolakannya terhadap mekanisme pasar karbon. Menurut Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, perdagangan karbon didasarkan pada lanskap dan izin konsesi kehutanan yang dikelola perusahaan.
Perdagangan karbon pertama kali digagas dalam Protokol Kyoto pada 2005. Perjanjian internasional PBB ini bertujuan mengurangi emisi karbon global dan mitigasi perubahan iklim. Namun mekanisme ini terus diperdebatkan. Salah satunya karena tetap mengizinkan perusahaan polutan menghasilkan emisi, lalu mengkompensasinya dengan membeli karbon (carbon offset) di negara lain yang menjual karbon.
“Selama perdagangan karbon dilakukan dengan model lanskap dan konsesi perizinan, pasti akan berdampak pada penggusuran, baik itu masyarakat adat maupun komunitas lokal. Karena mereka tinggal di dalam hutan ataupun menggantungkan penghidupan kepada hutan,” kata Uli kepada Betahita, Kamis, 10 Agustus 2023.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang diikuti berbagai aturan instansi terkait, termasuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik.
Uli menyebut saat ini beberapa konsesi restorasi ekosistem di Indonesia sudah mulai atau akan berdagang karbon. Salah satunya proyek Katingan di Kalimantan Tengah, yang merupakan salah satu proyek REDD+ terbesar di dunia. Proyek ini dikelola PT Rimba Makmur Utama (RMU) sejak 2013, dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) seluas 100.000 hektare untuk restorasi dan konservasi gambut Katingan atau proyek REDD+. PT RMU kembali mendapatkan lahan seluas 500.000 hektare untuk izin yang sama.
Proyek ini merupakan kemitraan antara PT RMU, Wetlands International, Puter Foundation, dan Permian Global. Kredit karbonnya sendiri dikeluarkan pada Mei 2017, lalu April 2019. Shell diketahui membeli karbon kredit dari Katingan. Pada September 2019, Volkswagen juga mengumumkan bahwa mereka akan membeli offset karbon dari proyek Katingan.
Menurut Uli, setidaknya terdapat 40.000 jiwa yang tinggal di 34 desa di sekitar area proyek Katingan. Selain itu, konflik di atas tanah ini terjadi yang menimpa masyarakat adat Dayak Misik. Walhi mencatat, Gubernur Kalimantan Tengah pada 2014 menyebut setiap keluarga Dayak diizinkan mengolah lima hektare lahan. Tetapi lokasi pasti tanah itu tidak disepakati.
Proyek serupa berada di Jambi, yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT REKI), atau lebih dikenal dengan Hutan Harapan. Perusahaan mendapatkan izin melalui SK Menhut No. 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 hektare.
Menurut catatan Walhi, proyek REDD+ ini mengalami kerusakan lantaran aktivitas pembuatan jalan angkut tambang batu bara sepanjang 26 kilometer dengan lebar 60 meter. Pada akhirnya, proyek ini mengakibatkan 1300 flora dan 620 fauna dari ekosistem hutan di Hutan Harapan terancam punah. Selain itu, kayu hutan sekunder yang nilainya lebih dari Rp 400 miliar juga hilang.
“Atas nama perdagangan karbon di wilayah ini, wilayah adat suku Anak Dalam dan kawasan transmigrasi dirampas dan ditetapkan sebagai wilayah konservasi dennga nilai jual hutan,” kata Kepala Departemen Advokasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian.
“Bila tidak ada kontrol dari masyarakat dan regulasi yang memadai, ini akan menjadi ancaman penyebab konflik agraria berikutnya,” kata Roni.
Walhi mencatat, terjadi kriminalisasi/penangkapan oleh aparat terhadap 19 masyarakat yang terkait dengan PT REKI periode November 2010 dan Oktober 2012.
Proyek perdagangan lainnya adalah Proyek Lahan Gambut Sumatra Merang di Sumatra Utara. Ini merupakan Proyek unggulan Forest Carbon dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Proyek ini memperoleh konsesi seluas 22.922 hektare. Saat ini saja ada 16 izin konsesi restorasi ekosistem dengan luasan 624.012 hektare.
Uli mengatakan, saat ini korporasi hanya perlu mengurus satu jenis izin kehutanan untuk melakukan beberapa jenis aktivitas eksploitasi.
“Misalnya saja, satu perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan-Hutan Tanaman dapat melakukan aktivitas pengambilan hutan alam, penanaman kebun kayu, dan berdagang karbon secara bersamaan, hanya dengan menyatakan apa saja aktivitas mereka tersebut dalam rencana kerja tahunan,” kata Uli.
Proyek karbon dengan izin multiusaha
Hal ini dilakukan oleh sejumlah proyek. Misalnya proyek perdagangan karbon milik Melchor Group di Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Merauke, yang memanfaatkan perizinan multiusaha. Dalam catatan Walhi, Melchor Group menandatangani kerjasama dengan PT Talisan Emas sebagai pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam), atau yang saat ini disebut PBPH-HT, seluas 54.000 hektare di Kepulauan Aru, Maluku.
Proyek bernama Proyek Talisan Emas ini juga telah mengkapling wilayah hutan seluas 591,957 hektare di Kepulauan Aru untuk proyek karbon. “Wilayah Aru adalah wilayah adat dari masyarakat Aru,” kata Uli.
Melchor juga memiliki proyek karbon di Merauke. Bekerja sama dengan Medco Group sebagai pemegang izin IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) seluas 170.000 hektare.
Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Muhammad Arman mengatakan, perdagangan karbon berpotensi merusak relasi antara masyarakat adat dengan hutan yang selama ini mereka jaga dan menjadi sumber penghidupannya. Relasi ini bukan hanya soal motif ekonomi, tapi juga religius, spiritual, dan kultural. Hutan menjadi identitas dan penanda budaya, yang seharusnya dikelola dan diwariskan turun-temurun kepada generasi mendatang.
“Ini tentu akan menyingkirkan masyarakat yang hidup di wilayah tersebut, serta melanggengkan konflik di wilayah ekstraksi pertambangan dan perkebunan sawit milik perusahaan,” kata Arman.
Selain itu, kebijakan karbon pemerintah menyatakan bahwa dalam konteks ini karbon dari hutan adalah milik negara. Ini kontras dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK 35) yang mengakui hutan adat dan wilayah adat, dan bukan milik negara.
“Pemerintah melupakan satu entitas dan seluruh warga negara yang ikut berkontribusi besar dalam menjaga hutan. Ini adalah upaya untuk mengambil alih kembali hutan masyarakat adat yang telah diakui dan diputus dalam Mahkamah Konstitusi,” kata Arman.
“Perdagangan karbon adalah siasat iklim yang keliru, karena tetap mengizinkan perusahaan polutan mengeluarkan emisi dan juga mengusir masyarakat adat dan komunitas lokal,” kata Uli.
“Seharusnya pemerintah mendorong pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat adat, dan memberikan dukungan agar melindungi wilayahnya dan mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Uli.
SHARE
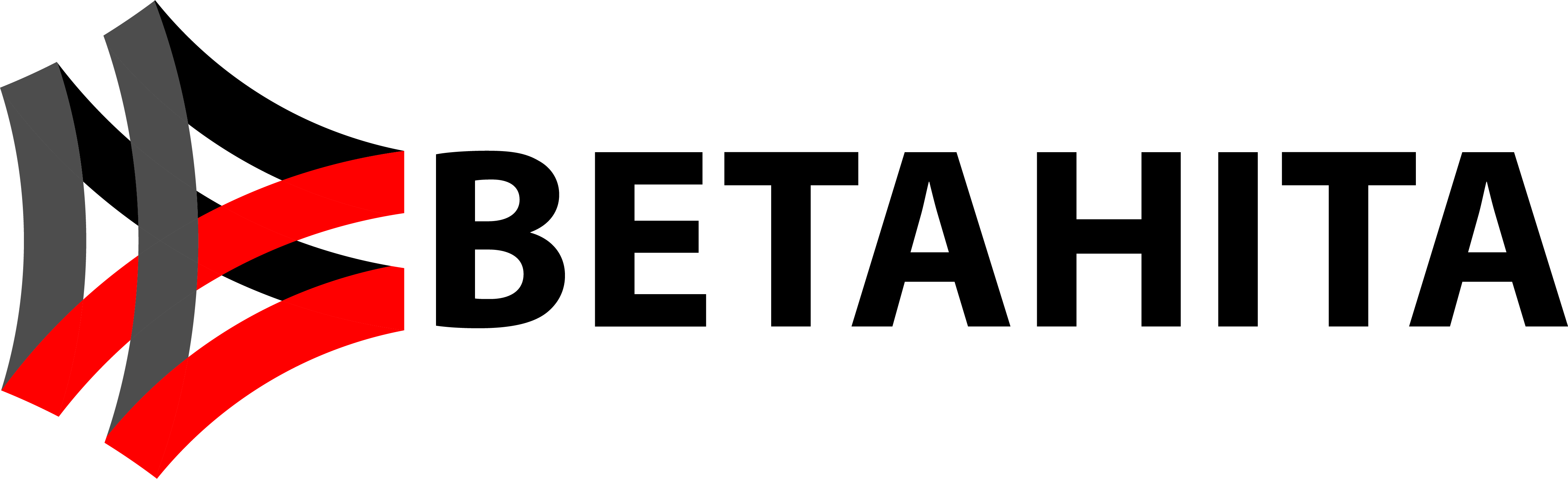


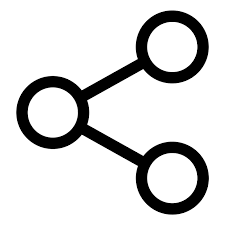 Share
Share

