Jatam: JETP Indonesia Jawaban yang Keliru atas Krisis Iklim
Penulis : Raden Ariyo Wicaksono
Iklim
Jumat, 16 Juni 2023
Editor : Sandy Indra Pratama
BETAHITA.ID - Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) dianggap bukan jawaban atau solusi yang benar atas persoalan krisis iklim di Indonesia, menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Terlebih banyak hal belum terjelaskan kepada publik terkait program JETP ini.
Dalam pernyataan resminya, Jatam menguraikan, rencana investasi JETP untuk Indonesia tidak akan berkontribusi penting pada koreksi atas pembesaran "sumbangan" emisi Indonesia dari industri energi. JETP sendiri yang mencakup hampir 20 miliar dolar hutang baru akan membebani keuangan negara untuk proyek-proyek yang sama-sekali tidak berhubungan dengan pemulihan krisis atau perlindungan atas ekonomi rakyat banyak.
Rencana investasi JETP dan transaksi bisnis, terutama dengan investor, akan berlangsung di dalam perpipaan aliran keuangan, informasi dan komoditi di bawah kendali industri, dan karenanya tidak akan memberikan manfaat besar apalagi perlindungan bagi warga di wilayah-wilayah operasi industri energi di kepulauan Indonesia.
"JETP tidak mungkin menciptakan keadilan sosial, apalagi ikut memulihkan krisis ekologis pada skala biosfera maupun pada skala kepulauan dan perairan Indonesia," kata Melky Nahar, Koordinator Jatam Nasional, Kamis (15/6/2023).

Melky menjelaskan, rencana-rencana investasi beserta target-target waktu capaian dalam "ekonomi-perubahan-iklim" skala global adalah serangan dan ancaman nyata pada jaminan keamanan bentang-bentang air, lahan penghasil pangan dan sumber-sumber kehidupan rakyat lainnya.
Khususnya yang menyangkut pembesaran wilayah ekstraksi dan pasar tangkapan dari industri energi, termasuk pembesaran ladang-ladang ekstraksi geothermal, mineral baterai, bahan-bakar nabati dan jenis energi terbarukan lainnya.
"JETP, beserta berbagai program pembiayaan multilateral lainnya untuk investasi industri energi dan industri ekstraktif dengan dalih menyelamatkan dunia dari krisis iklim merupakan modus operandi dari perangkap hutang, perangkap perdagangan instrumen keuangan karbon, dan sepenuhnya berwatak kolonial," ujar Melky.
Apa yang Salah dengan JETP?
Lebih jauh Melky menguraikan, JETP merupakan rencana investasi industri keuangan/pembiayaan global. Operator JETP untuk Indonesia, dalam satu tahun ini, harus merumuskan aspek-aspek kunci kebutuhan pembiayaan, termasuk pensiun dini pembangkit listrik dan tambang batu bara serta peluasan penerapan teknologi energi bersih yang memudahkan transisi ke produksi konsumsi energi rendah karbon.
Tetapi belum cukup banyak informasi dan kajian yang dikemukakan dan dibicarakan bersama warga masyarakat Indonesia tentang hal ikhwal rencana pembiayaan JETP tersebut. Termasuk mengenai risiko-risiko apa saja yang harus dikemukakan terbuka oleh pihak pengelola JETP kepada publik.
"Baik risiko keuangan, risiko eskalasi bencana bagi warga wilayah-wilayah yang dibebani program JETP, atau risiko justru tidak tertanganinya masalah-masalah dari dalam perusahaan-perusahaan industri energi sendiri?" kata Melky.
Melky mengatakan, Indonesia bisa belajar dari paket JETP untuk Afrika Selatan, sasaran pertama promotor kemitraan. Dari investasi senilai USD8,455 miliar, 96 persen JETP Afrika Selatan bentuknya pinjaman konsesional dan pinjaman komersial serta jaminan hutang. Hanya empat persennya berupa dukungan hibah.
Perbandingan hibah/hutang dari keenam investornya (CIF/ACT, Inggris, UE-Bank Investasi Eropa, AS, Perancis, Jerman) berkisar antara 0.3 persen (Perancis) sampai 25.7 persen (Jerman). ESKOM sebagai PLN-nya Afrika Selatan sendiri terbelit krisis mendalam, dan rerantai pasokan pengadaan daya sendiri pun sampai sekarang tidak pasti.
Untuk Indonesia, lanjut Melky, kata-kunci "ET" dalam akronim JETP sendiri perlu publik pertanyakan. Di sepanjang tiga dekade terakhir (1990-2018), pertumbuhan emisi gas rumah-kaca Indonesia adalah 5 kali lipat untuk kelistrikan dan transportasi, dan 4 kali lipat untuk manufaktur atau konstruksi.
"Lalu bagaimana perumusan kebutuhan energi berlangsung? Untuk melayani kepentingan apa dan siapa?" Melky bertanya-tanya.
Bicara soal transisi industri energi, Melky mengungkapkan, bauran konsumsi batu bara dalam negeri dalam rentang waktu 1985-2020 naik dari ±10 persen ke ±40 persen. Indonesia mengekspor 70-80 persen hasil ekstraksi batu bara, untuk dibakar di beberapa negara pembelinya.
Kementerian ESDM sendiri, katanya, terus menaikkan target ekstraksi batu bara, dari 594 juta ton pada 2020 menjadi 20 persen ke 697 juta ton pada 2023. Artinya tidak lain adalah kenaikan emisi terkoordinir dari industri batu bara Indonesia.
"Kalau pasokan listrik dianggap penting sebagai sumber emisi, hari ini kebutuhan puncak Indonesia adalah ±40GW, sementara besaran pasokan listrik adalah ±70GW. Berapa gigaton emisi CO2 yang sebetulnya tidak perlu dihasilkan oleh industri energi listrik tersebut?" lanjut Melky.
Melky heran, mengapa pemerintah justru membesar-besarkan cerita soal rencana pensiun dini belasan PLTU, termasuk lewat pembakaran campuran dengan biomassa, beserta inovasi kategori perkebunan/konversi hutan, dari HTI menjadi HTE (hutan tanaman energi). Apalagi saat ini digencarkan pula promosi resmi transaksi keuangan antar-operator atau pemilik PLTU sebagai mekanisme palsu penurunan emisi lewat perdagangan instrumen keuangan karbon.
Sama seperti batu bara, imbuh Melky, tiap tahun target lifting minyak dan gas fosil terus naik, bertolak belakang dengan berbagai janji hebat kontribusi reduksi emisi nasional. Ironisnya, dua sumber emisi biang krisis iklim bumi ini bahkan tidak disebut-sebut dalam kata transisi energi dari JETP.
Ini Soal Politik, Bukan Soal Teknis
Melky menyebut tiga kata-kunci dalam JETP, transisi-energi, adil, dan kemitraan, sarat dengan muatan politik kepentingan negara utara/kaya/industri-maju sebagai penguasa aliran keuangan dan rantai ekonomi global, di hadapan krisis perubahan iklim bumi. Setidaknya terdapat tiga agenda yang mewakili kepentingan tersebut.
Pertama, pengalihan perhatian dan pengerahan kesepakatan negara-negara anggota PBB, dari soal penghentian ekstraksi, pengolahan dan konsumsi sumber-energi fosil, yaitu minyak bumi, gas bumi dan batu bara, sebagai sumber penyebab utama bencana iklim, menjadi persoalan transaksi kompensasi keuangan atas pembesaran emisi dari industri energi fosil, terutama atas nama mekanisme ekonomi rendah karbon, ekonomi hijau, pembangunan bersih, pembelian "hak mencemari" dari perusahaan pemegang konsesi stok cebakan karbon yang beroperasi di sabuk tropis, dan penerapan teknologi pereduksi cemaran dari pembakaran sumber-energi fosil.
"Kalau mau terus mencemari udara tanpa berbuat apa-apa, bayar. Dalam penjungkir-balikan akal sehat seperti itu, perusahaan-perusahaan energi fosil raksasa dan industri yang bergantung padanya bahkan akan bisa mengaku telah mencapai emisi Nol sambil terus memperbesar semburan gas rumah-kaca," terang Melky.
Agenda kedua, pembesaran dan perluasan pasar industri energi beserta rantai industri ekstraktif, infrastruktur teknologi dan keuangan atau pembiayaan yang berkelindan dengannya. Melky bilang, sasaran utamanya memang negara-negara selatan (disebut juga wilayah pasar-berkembang atau emerging markets), sebagai pasar tangkapan maupun sebagai zona-pengorbanan dalam pendudukan dan pembongkaran bentang daratan dan perairannya untuk ekstraksi mineral vital bagi produksi dan konsumsi energi terbarukan.
Ketiga, penyiapan segenap protokol penjaminan keamanan kepentingan investasi jangka panjang atas wilayah-wilayah koloni industri--terutama koloni industri energi--dari negara Utara, termasuk pembaruan sistem transaksi dan penghitungan pendapatan nasional, mekanisme dan instrumen regulasi, akses bebas ke bagian manapun dari wilayah kedaulatan negara yang bisa dieksploitasi, dan jaminan penguasaan ruang jangka-panjang.
"Tidak mungkin diselipkan gagasan keadilan dalam skema JETP, dan yang disebut sebagai kemitraan akan lebih tepat disebut sebagai relasi kolonial-imperial antara patron politik dan keuangan dengan negara-negara kliennya," imbuh Melky.
Seperti diketahui sebelumnya, pada 15 November 2022 lalu dalam pertemuan puncak pemerintah negara-negara anggota klub G-20, Pemerintah Indonesia menandatangani surat kesepakatan pendanaan dengan badan-badan peminjam dana internasional dan pemerintah negara-negara kaya. Tujuan kesepakatan itu untuk meningkatkan konsumsi energi terbarukan dan mengurangi ketergantungannya pada batu bara, di bawah skema JETP.
Pada saat yang bersamaan, konferensi para pihak Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim ke-27 di Mesir menyepakati rincian aturan perdagangan jatah kompensasi emisi karbon, bagian dari Pasal 6 Kesepakatan Paris (COP 21, 2015). Pemerintah Indonesia adalah pengurus negara kedua yang menyepakati skema JETP, setelah Pemerintah Afrika Selatan dua tahun sebelumnya.
Rencana investasi JETP untuk Indonesia terdiri dari USD10 miliar dari IPG (International Partners Group, terdiri dari Perancis, Jerman, Inggris, AS, Uni Eropa), serta USD10 miliar hutang di bawah koordinasi GFANZ (Gugus Kerja Aliansi Keuangan Glasgow untuk Net Zero, terdiri dari HSBC, Standard Chartered, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, MacQuarie, MUFG).
Kerangka JETP sendiri tak terpisahkan dari alokasi dana pinjaman CIF (Climate Investment Fund/Dana Investasi Iklim) dari Group Bank Dunia (2008), termasuk program pinjaman CTF (Clean Technology Fund/Dana Teknologi Bersih) bagi swasta untuk investasi geothermal, baterai, tenaga surya, serta program pinjaman ACT (Accelerating Coal Transition/Mempercepat Transisi batu bara) dengan empat negara sasaran awal yaitu India, Indonesia, Filipina dan Afrika Selatan.
SHARE
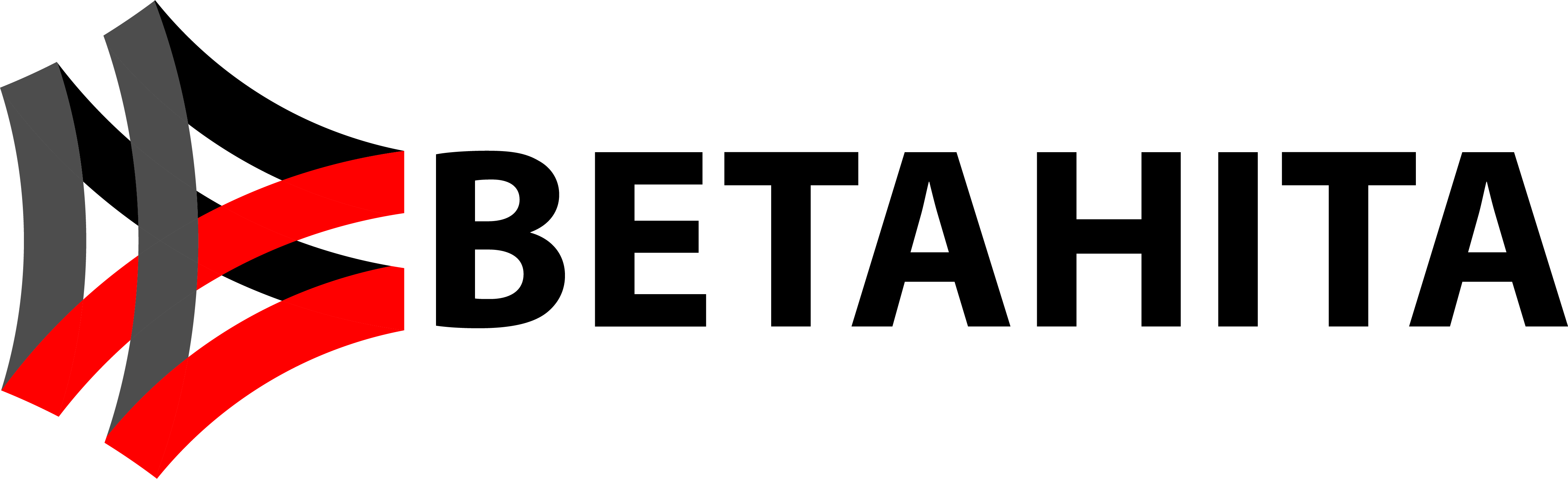


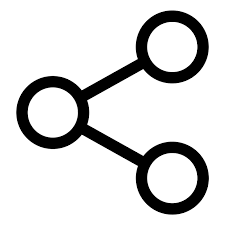 Share
Share

