Setengah dari Kepemilikan Kebun Sawit Indonesia Tidak Terlacak
Penulis : Kennial Laia
SOROT
Kamis, 14 Mei 2020
Editor :
BETAHITA.ID - Pemilik perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar tidak diketahui. Hal ini menyebabkan sulitnya melacak rantai pasok dari industri hulu ke hilir serta afiliasi kebun sawit dengan perusahaan pemilik fasilitas pengolahan atau refinery.
Hal itu tertuang dari hasil kajian Trase.earth, Auriga, dan Universitas Santa Barbara. Laporan berjudul “Kepemilikan dan Dominasi Korporasi pada Rantai Pasok Minyak Sawit di Indonesia” itu menemukan lebih dari 50 persen luasan kebun sawit Indonesia tidak jelas pengelola atau pemiliknya.
“Kalau melihat data yang masuk ke BPS dan identifikasi HGU, dan AHU, ternyata ada 50 persen itu masih antah berantah. Yang diketahui hanya kelompok teratas saja,” kata Peneliti Trase Giorgio Budi Indarto dalam diskusi virtual Ngopini: Mengurai Peta Pemain Industri Sawit Nasional yang diadakan Auriga,4 Mei 2020.
“Padahal ini penting untuk konteks keberlanjutan,” katanya.

Menurut Giorgio, informasi keterlacakan data itu dapat membantu Indonesia merencanakan tata kelola sawit seperti program peremajaan sawit rakyat yang capaiannya rendah. Program PSR ini pun dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Untuk diketahui, saat ini pemerintah memiliki peta tutupan luas perkebunan sawit seluas 16,4 juta hektare yang dapat diakses publik.
“Identifikasi kepemilikan juga penting karena di situlah konteks keberlanjutannya. Kalau saat ini, masih banyak pemain besar yang berkedok sebagai petani,” ujar Giorgio. Proyek sawit berkelanjutan ada dalam Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau ISPO.
Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah, mengatakan, data sawit yang komprehensif penting untuk pengembangan sektor kelapa sawit itu sendiri.
“Sumbangan sawit terhadap ekonomi Indonesia itu cukup signifikan. Untuk pengembangannya, data adalah syaratnya,” ujarnya.
Alin juga menyoroti struktur pasar industri sawit hilir yang saat ini masih berupa oligopoli di hilir dan oligopsoni di hulu. Menurutnya, kondisi itu memungkinkan perusahaan besar mengatur harga di seluruh tahapan rantai pasok industri sawit.

“Secara teori ekonomis, kondisi oligopoli dan oligopsoni dapat menimbulkan kerugian. Mulai dari petani yang mengalami tekanan harga untuk tandan buah segar, harga minyak sawit di level konsumen, dan bahkan pemerintah terkait insentif biodiesel,” katanya.
Komitmen keberlanjutan penting
Hasil riset Trase menunjukkan, terdapat lima korporasi besar yang mendominasi dua pertiga dari total kapasitas pengilangan dan volume ekspor sawit Indonesia. Mereka adalah Wilmar, Sinar Mas, Musim Mas, Royal Golden Eagle, dan Permata Hijau. Sisanya, tidak tercantum.
Menurut Giorgio, data kepemilikan perkebunan kelapa sawit penting untuk memastikan komitmen NDPE atau No Deforestation, No Peat Development and Exploitation. Komitmen ini bertujuan agar praktik perkebunan sawit lebih ramah lingkungan.
Temuan dari Trase, Auriga, dan UCSB, sebanyak 80 persen perusahaan sawit tidak terlacak. Minimnya keterlacakan ini mulai dari tingkat kebun hingga perusahaan afiliasi.
“Artinya, kita tidak bisa melihat datanya. Tapi bukan berarti yang 80 persen itu ilegal, tapi lebih ke tidak tercatat. Kalau tercatat rapi, traceability-nya lebih keliatan,” ujar Giorgio.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Agam Fatchurrochman mengatakan, jumlah pemain sawit di hilir lebih sedikit sehingga lebih mudah ditata. Pasalnya, modal biaya pembukaan fasilitas pengolahan atau kilang minyak sawit sangat tinggi. Akibatnya, hanya perusahaan bermodal besar yang dapat berinvestasi.
Agam membandingkan ongkos membangun kilang yang mencapai Rp3 triliun dengan biaya pembuatan pabrik kelapa sawit sekitar Rp300 miliar. Sementara itu di sektor hulu, biaya pembukaan kebun pun relatif murah.
“Dari situ kita mengetahui perbedaan biaya yang sangat jauh,” tutur Agam.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kodrat Wibowo mengakui keruwetan data kepemilikan kebun sawit di Indonesia. Menurutnya, pihaknya kesulitan memetakan persaingan karena banyak pemain besar yang tidak masuk radar KPPU.
Namun, saat moratorium sawit terbit, KPPU mendapat sedikit kejelasan. Kodrat mengatakan, saat itu terdapat beberapa perusahaan besar yang mengakuisisi perusahaan kecil pemilik lahan. Upaya ekstensifikasi tidak langsung itu pun dilakukan secara terstruktur.
“Banyak dari transaksi ini yang terlambat dilaporkan ke KPPU. Alasannya, mereka tidak tahu atau merasa itu bukan kewajiban,” kata Kodrat.
“Faktanya, kalau di persidangan, penjelasan mereka atas transaksi ini adalah untuk bersiap-siap antisipasi stabilitas harga sawit internasional. Dari pengataman kami, para pengambil alih itu sebenarnya berafiliasi dengan pemain besar,” jelasnya.
Hal ini pun sulit dipantau KPPU karena tidak punya kewenangan lintasnegara, terutama terhadap perusahaan yang terdaftar di negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura.
“Kalau kami memiliki kewenangan lintasyuridiksi, mungkin kami bisa menutupi kekosongan itu. Apalagi banyak pemain besar yang tidak bisa kami sentuh, yang masih bersaing dalam kacamata oligopoli dan berpotensi kartel,” katanya.

Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura Kementerian Koordinator Perekonomian Muhammad Saifulloh mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 telah mengatur sertifikasi ISPO. Amanatnya, seluruh pelaku usaha termasuk kebun sawit harus tersertifikasi lima tahun ke depan.
“Namun, apa ini bisa terpenuhi dalam lima tahun? Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” katanya. Di sini, data dan informasi kepemilikan perkebunan sawit menjadi krusial.
Saifulloh mengatakan, ISPO menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola dan membuka akuntabilitas serta transparansi terkait traceability.
“Kalau itu ada, maka seluruh pasokan tandan buah segar dapat ditelusuri. Maka, pekerjaan kita sudah selesai 70 persen. Tinggal kebun sawit dalam kawasan hutan,” katanya.
SHARE
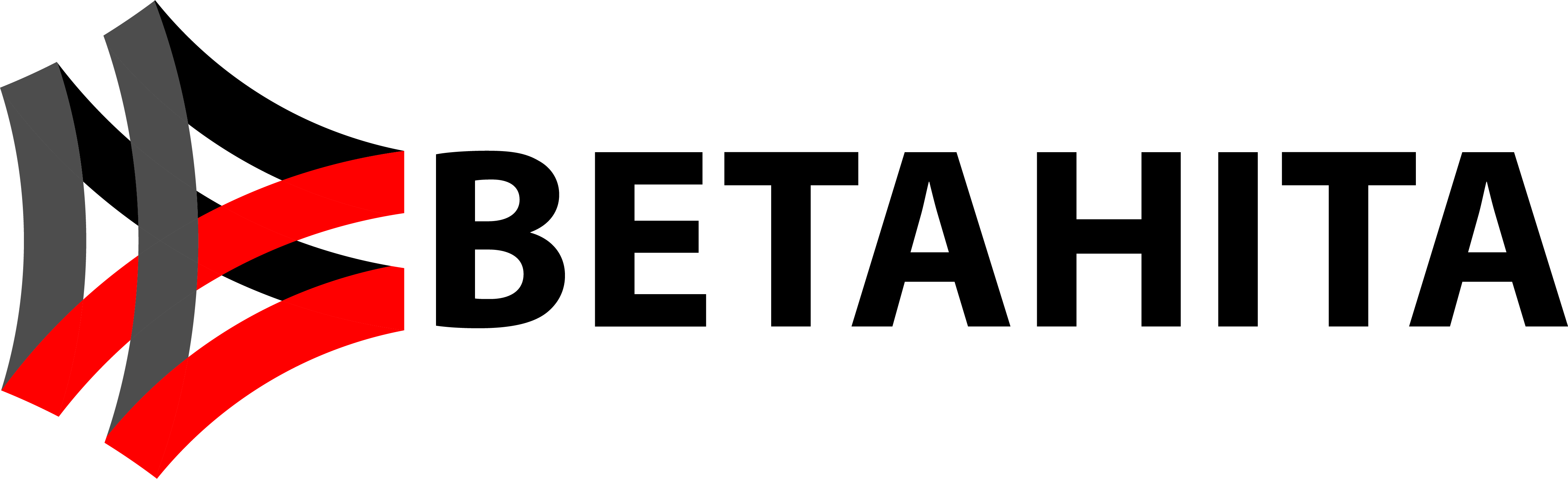


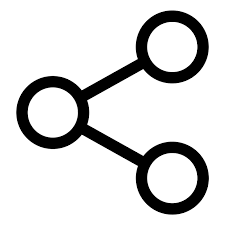 Share
Share
