Biodiesel Terkembang, Hutan Alam Tertebang
Penulis : Sesilia Maharani Putri - Peneliti Perkebunan Yayasan Auriga Nusantara
OPINI
Sabtu, 22 Februari 2025
Editor : Yosep Suprayogi
BETAHITA.ID - Pada Agustus tahun lalu, siaran pers pada laman resmi ESDM mengumumkan bahwa pemerintah akan mempercepat implementasi B40 berbasis sawit mulai Januari 2025, meskipun implementasinya ditunda hingga Maret 2025. Melalui pernyataan kepada media, kebutuhan biodiesel untuk memenuhi mandatori tersebut awalnya ditaksir mencapai 17,57 juta kL, meski kemudian taksiran tersebut berkurang menjadi 15,6 juta kL.
Berjalannya program B40 akan memberikan tekanan bagi industri sawit untuk menyediakan lebih banyak crude palm oil (CPO), sebagai sumber utama bahan baku biodiesel hingga kini. Merujuk pada data BPS, rerata produksi CPO di Indonesia pada rentang 2019 hingga 2022 sebesar 46,2 juta ton, dengan rerata ekspor sebesar 27,4 juta ton. Sehingga jumlah CPO yang tersedia untuk produksi biodiesel adalah 18,7 juta ton, dengan asumsi produksi biodiesel mengandalkan CPO dalam negeri.
Dengan menggunakan skema business as usual (BAU), dibutuhkan sebanyak 14,9 juta kL biodiesel setara dengan 16,6 juta CPO untuk memenuhi B40. Penambahan tersebut akan membebani kebutuhan CPO dalam negeri, dengan hanya menyisakan 2 juta ton CPO untuk industri lainnya. Berkurangnya jumlah CPO dalam negeri ini mencapai 2 kali lipat dibanding saat program B35 dilaksanakan. Cepat atau lambat realisasi program B40 akan mengganggu pemenuhan CPO untuk industri lain.
Lebih parah lagi jika program B40 dijalankan sesuai dengan taksiran awal pemerintah, dibutuhkan sebanyak 17,5 juta kL biodiesel atau setara dengan 19,3 juta ton CPO. Berarti Indonesia akan kekurangan 567 ribu ton CPO saat program ini dilaksanakan. Makin tak masuk akal lagi jika program biodiesel dilanjutkan hingga B50 bahkan B100, produksi sawit Indonesia saat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan Industri biodiesel terhadap bahan baku.

Jalan cepat yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah mengurangi jumlah ekspor atau melakukan perluasan lahan. Meski pemerintah mengatakan bahwa kebutuhan CPO untuk B40 dapat disubstitusi dari pengurangan ekspor, rasanya hal tersebut tak mungkin terjadi. Pasalnya dana yang didapatkan oleh BPDPKS selaku pemberi subsidi biodiesel berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya.
Belum lagi wacana terbaru pemerintah yang ingin menggabungkan pengelolaan dana untuk komoditas perkebunan lain seperti kakao dan kelapa di bawah BPDPKS. Meski belum jelas asal sumber dana yang akan disalurkan nantinya, kemungkinan besar dana untuk keduanya akan ditopang oleh dana sawit.
Keengganan pemerintah melanjutkan moratorium sawit, hingga wacana penambahan 1 juta hektare lahan sawit di Sulawesi, menunjukkan bahwa sejak awal intensi pemerintah adalah perluasan lahan. Bahkan pasca pemerintahan baru isu pembukaan 20 juta hektare lahan untuk pangan dan energi kian santer. Tuntutan untuk melancarkan program biodiesel ini akan jadi salah satu pemicu utama pembukaan hutan dan degradasi lahan akibat sawit. Ketika ambisi pemenuhan mandatori sawit terus dijalankan, Indonesia akan kekurangan 22 juta ton CPO untuk memenuhi B100. Kekurangan tersebut akan setara dengan ekspansi lahan seluas 5 juta hektare lahan.
Pernyataan problematik Presiden Prabowo pada Desember lalu untuk terus menambahkan kebun sawit, dan tak risau dengan deforestasi, seolah jadi ramalan, bahwa ke depan konversi hutan alam untuk sawit akan makin masif. Hal ini bahkan tercermin pada deforestasi yang terjadi di 2024, deforestasi untuk pembangunan kebun sawit teridentifikasi seluas 37.483 hektare, atau 14% dari total deforestasi di Indonesia pada 2024.
Deforestasi di pulau sentra sawit terutama Sumatera, menunjukkan peningkatan deforestasi sebesar 2 kali lipat dibanding 2023. Parahnya deforestasi ini bahkan tidak hanya menyasar pada konsesi izin sawit, namun di dalam konsesi kehutanan.
Ketiadaan safeguard jelas akan perlindungan terhadap hutan makin memperbesar celah perusakan hutan ke depan. Cara pandang terhadap hutan sebatas komoditas dengan nilai ekonomi hanya mempercepat krisis iklim yang kini tengah berlangsung. Alih-alih mendorong upaya pengembangan biodiesel menggunakan bahan baku bebas deforestasi, kebijakan yang kini dijalankan justru mempercepat kehilangan hutan Indonesia.
Jika pemenuhan bahan baku nabati tidak melulu mengedepankan keuntungan perusahaan besar, maka upaya pengembangan terhadap teknologi dan diversifikasi sumber bahan baku harus dilakukan secara optimal. Sehingga ketergantungan biodiesel terhadap sawit dapat dikendalikan dan meminimalisasi pembukaan lahan untuk biodiesel.
Selain itu, komitmen perusahaan sangat diperlukan agar produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi terhadap rantai pasok biodiesel misal, agar pasar dapat menakar sejauh mana kesiapan Indonesia memenuhi bahan baku sawit bagi biodiesel. Hal tersebut dapat juga digunakan sebagai bentuk tanggung jawab produsen sebagai bukti bahwa produknya bersih dari perusakan lingkungan.
Hutan alam hilang demi biodiesel
Biofuel merupakan bahan bakar yang diperkenalkan sebagai alternatif pengganti solar, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah. Biodiesel sendiri merupakan salah satu turunan produk biofuel. Emisi yang dihasilkan oleh biodiesel, baik CO, CO2, HC, asap, dan lainnya, lebih rendah secara signifikan dibanding emisi yang dihasilkan oleh solar. Meski demikian penelitian lain mengungkap, biodiesel memang menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan solar, namun jika tidak melibatkan deforestasi.
Emisi karbon yang dilepaskan oleh lahan dan tumbuhan akibat konversi hutan alam maupun vegetasi alami menjadi sawit, melepaskan sejumlah besar karbon. Sejumlah besar karbon ini kemudian kerap disebut sebagai “hutang karbon” yang harus dibayar dalam waktu lama.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Fargione et al, bahkan jika hutang karbon dibayar 7.1 Mg CO2e/tahun, dibutuhkan waktu 86 tahun untuk membayar hutang karbon akibat konversi hutan tropis dataran rendah menjadi sawit di Indonesia dan Malaysia. Waktu yang dibutuhkan untuk membayar hutang karbon akibat konversi gambut bahkan jauh lebih lama yaitu 423 tahun.
Tak dapat dipungkiri bahwa emisi yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar biodiesel lebih rendah dibanding kendaraan berbahan baku solar. Merujuk pada siaran pers Kementerian ESDM, berkat biodiesel Indonesia mampu menurunkan emisi sebesar 27,8 juta ton CO2 e sepanjang 2022. Namun yang luput dilihat adalah berapa besar emisi yang dihasilkan dibalik produksi biodiesel ini sendiri.
Penulis menemukan bahwa 17 dari 23 kilang yang memproduksi biodiesel saja secara langsung maupun tidak menghasilkan 17,8 juta CO2 e di tahun yang sama. Emisi tersebut berasal dari perubahan penutupan lahan menjadi sawit (land use change) atau degradasi, penurunan muka air gambut, dan kebakaran di lahan gambut. Paparan emisi tersebut hanya melihat perubahan pada lahan yang ditanami sawit, tanpa melihat emisi yang dihasilkan sepanjang proses produksi CPO menjadi FAME dan biodiesel.
Grup-grup produsen biodiesel pada 2023 bahkan terhubung pada ratusan ribu hektare perusakan hutan. Ribuan hektare deforestasi tersebut berasal dari izin-izin yang teridentifikasi sebagai supplier kilang produsen biodiesel dan anak usaha pada grup produsen biodiesel.
Berdasarkan supplier ke kilang biodiesel, penulis mengidentifikasi seluas 476 ribu hektare deforestasi yang terhubung ke 7 grup usaha biodiesel. Sedangkan pada anak usaha grup tersebut penulis menemukan seluas 165 ribu hektare deforestasi yang terhubung ke 10 grup usaha. Data tersebut berasal dari deforestasi yang terjadi sejak program biodiesel dimulai pada 2006 hingga 2021.
Saat ini terdapat 2,4 juta hektare tutupan hutan alam di dalam izin sawit di Indonesia. Seluas 120 ribu hektare di antaranya berada dalam konsesi yang memasok sawit ke perusahaan biodiesel. Tanpa intensifikasi, hutan-hutan ini akan terancam deforestasi demi pemenuhan kebijakan biodiesel. Tiga provinsi teratas dengan hutan alam dalam konsesi pemasok biodiesel berada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Hutan alam di konsesi pemasok biodiesel di ketiga provinsi ini mencapai 63 ribu hektare, atau lebih dari separuh total tutupan hutan di dalam konsesi sawit pemasok biodiesel. Patut dicatat bahwa ketiga provinsi ini juga termasuk 10 besar provinsi pemilik tutupan hutan terluas di Indonesia, sehingga potensi deforestasi di provinsi ini demi ekspansi monokultur seperti kebun sawit masih sangat terbuka di provinsi-provinsi ini.
Dengan begitu besarnya potensi kehilangan hutan alam dan deforestasi ke depan, pemerintah perlu memikirkan kembali penanggulangan risiko dari kebijakan ini. Alih-alih menggebu-gebu mengejar penambahan bauran dengan embel-embel mengurangi emisi karbon. Data di atas cukup jelas bahwa kebijakan biodiesel saat ini masih bukanlah solusi penurunan emisi karbon yang diidamkan pemerintah.
SHARE
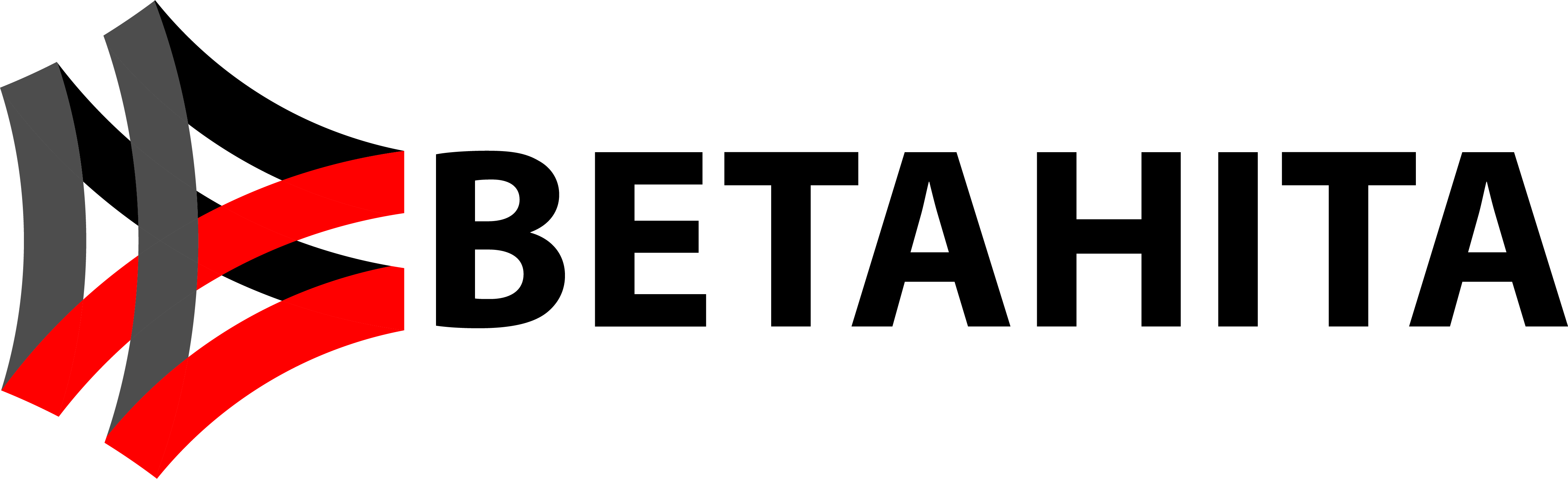


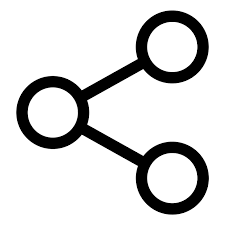 Share
Share

